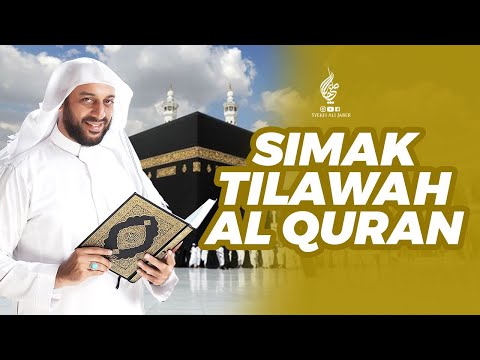PRIMADONA CELL
Minggu, 14 Maret 2021
Sabtu, 13 Maret 2021
Bekerjalah untuk Dunia Dan Akhirat
Dunia sebentar lagi akan berakhir. Manfaatkanlah akhir waktumu Untuk mencari bekal pada perjalanan berikutnya. JANGAN MENJADI ORANG MISKIN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT PUN MISKIN. SETIDAKNYA MISKIN DI DUNIA NAMUN KAYA DI AKHIRAT.
Secepat-cepatnya Pembalap, yang menang adalah yang paling pertama sampai Finish. JANGANLAH PUTUS ASA ATAS MASA LALUMU. KARENA RAHMAT DAN AMPUNAN ALLOH YANG KITA HARAPKAN.
Tanamlah apa yang dapat kita tanam. Karena kitalah yang akan memetik hasilnya. TUHAN TIDAK MENGAMBIL KEUNTUNGAN DAN TAKAN PERNAH RUGI KARENA KITA. DIALAH YANG PUNYA SEGALANYA, DAN MAHA KUASA ATAS SEGALANYA. DZAT YANG MAHA PERKASA DAN YANG MAHA MULIA.
لااله الّاهوا.
,عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم..
Kamis, 21 Maret 2019
GENERASI IDAMAN DATOK (by : Remaja Loloan)
Kutipan H. Baginda Ali.
Catatan dari pelaksanaan Festival Budaya Loloan ( FBL ).
Hal yang dirasa berat saat ini pada Entitas Kampung Islam Loloan Jembrana Bali adalah upaya mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan tradisi Nenek Moyang mereka apa lagi komunitas ini telah eksis dan berlangsung dengan rentang sejarah kurang lebih berkisar 350 tahun lalu. Suatu bentangan waktu yang tidak pendek dalam mempertahankan tradisi di suatu komunitas yang dinamis dan di tengah gelombang arus budaya asing dan era komunikasi digital yang semakin menggila. Lagi pula komunitas yang tergolong minoritas ini justeru berada di tengah-tengah kaum mayoritas di Bali. Meskipun saat ini masih ada yang tersisah dengan pasti yaitu berupa beberapa relik reliknya yang bersifat statis yang masih bisa disaksikan berupa barang-barang antik produk budaya Bugis-Makassar di abad ke XVII sedang catatan sejarahnya hanya sedikit yang terukir di atas kertas.
Catatan kuno dan kini yang ada tentang Loloan ini antara lain Manuskrip milik Datuk Haji Siraj yang ditulis dengan huruf Arab pegon tahun 1935 M, diktat yang ditulis oleh I Wayan Reken tahun 1979 M, diktat yang ditulis oleh Ust. Husin Abdul Djabbar 2010 M, adalah merupakan sumber lokal tentang komunitas yang unik di Bali ini. Adapun sumber Asing hanya ada dua antara lain buku yang ditulis oleh C. Lekkerkerker, ( Belanda ) yang berjudul Bali En Lombok, Overzicht Der Literatuur Omtrent Deze Eilanden Tot Einde, tahun 1919 M. dan buku yang ditulis oleh Williard A. Hanna ( Amerika ) yang berjudul Bali Chronicles tahun 1935.
Dalam merekontruksi bangunan sejarah komunitas Kampung Loloan yang berawal dari abad ke XVII sampai ke sini tentu lebih banyak berbasis Oral Story ( cerita dari mulut ke mulut di setiap generasi ) dari pada Wraiting Story karena sedikitnya sumber tertulis baik lokal maupun asing. Hal ini yang menjadi kemudian subyektifitasnya tidak bisa dihindarkan karena bisa jadi kontroversi keterangan satu sumber dari sumber lainya. Demikian juga para Datok moyangnya sebagai bagian dari imforman pelaku sejarah sudah banyak yang telah tiada.
Langkah lain yang harus dilakukan oleh komunitas ini adalah upaya memperkenalkan produk-produk budaya leluhurnya agar tidak menjadi generasi yang missinglink terhadap leluhurnya yang telah membentuk inclave di pulau Bali ini . Untuk itu tentu kita sangat mengapresiasi prakarsa dari Generasi Muda Loloan Jembrana ini dalam upaya melestarikan warisan Budaya dan Tradisi Pendahulunya sejak abad ke XVII dengan melaksanakan agenda tahunan Fastival Budaya Loloan yang bertema “Pentas Loloan Tempoe Doeloe”. minimal dari acara ini sebagai ajang untuk dapat memperkenalkan produk Budaya nenek moyangnya baik berupa Benda (Tangabel) maupun Non Benda ( Non Tangabel ) kepada generasi sekarang agar menjadi inpirasi dan motivasi bagi mereka dalam membangun kampung ini di masa yang akan datang agar menjadi “Generasi Idaman dan Harapan Datok”.
Pesta yang bergelap-gelapan ini benar-benar menggambarkan nuansa di masa 3,5 abad silam di mana waktu itu Kampung Loloan Jembrana dan umumnya pulau Bali masih berupa hutan belantara akses antara satu daerah dengan daerah lainnya hanya ditempuh lewat jalur laut dan perkampungan pun masih jarang untuk daerah Jembrana yang ramai hanya di seputaran kampung Loloan ini saja oleh karena di situ ada Dermaga / Pelabuhan utama Jembrana dan Pasar umum dan dikunjungi pendatang dari luar daerah sedang di tempat lainnya hamper tidak ada keramaian.
Di sisi lain bahwa Pesta Rakyat ini adalah sebagai salah satu agenda wisata budaya yang sangat mungkin untuk dikembangkan di masa mendatang. Oleh karena acara ini banyak menyimpan hal-hal unik yang bisa dikemas menjadi obyek Human Interest di Pulau Bali.
Sebagimana halnya Produk Budaya Suku Bugis-Makassar di daerah lain telah berhasil menjadikannya sebagai event pariwisata provinsi misalnya produk budaya “Mappanre tasi” ( pasta laut ) warisan budaya suku Bugis Wajo di Pagatan Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang awalnya hanya pesta rakyat lokal lalu dikemas sedemikian rupa yang akhirnya menjadi agenda wisata Kalimantan Selatan setelah Budaya Pasar terapung Banjarmasin.
Demikian pula Bahasa Melayu Loloan ( Base Loloan ) yang sudah menjadi salah satu Bahasa Daerah Nusantara tersendiri dalam rumpun Bahasa Melayu hal yang wajib hukumnya untuk dilestarikan penggunannya. Menurut Dr. Sumarsono dalam disertasinya yang telah diujikan di Universitas Indonesia 1993 yang mengangkat tema tentang “Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan” bahwa bahasa ini sangat unik keberadaannya dan yang paling utama keunikannya adalah bahwa bahasa ini bisa bertahan berabad-abad lamanya justeru di tengah pengguna bahasa Mayoritas yaitu bahasa Bali pada hal masyarakat Loloan sendiri adalah pengguna bahasa Dwilingual yang menyebabkan bahasa ini dengan penuturnya terjadi interaksi Extralingual.
Tentu juga kita perlu mengapresiasi atas prakarsa Bapak Eka Sabara yang telah bekerja sama dengan Bapak MR. Fauzi untuk menyusun Kamus BAHASA MELAYU LOLOAN – INDONESIA yang saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Kalau tidak ada upaya ini tentu Bahasa Melayu Loloan sedikit-demi sedikit akan tergerus yang akhirnya bisa menghilang tanpa bekas seperti nasibnya bahasa Melayu Ampenan Lombok yang sudah hampir punah saat ini pada hal mungkin saja komunitas mereka telah ada sebelum bahasa Melayu Loloan digunakan.
Di lanjutkan dengan diskusi.
Eka Sabara Salut ulasan yg singkat padat dan sistematik...Wakhaji
Baginda Ali bravo setelah sy coba telusuri ternyata dimasa Arung Matoa Wajo ke 23 (1658-1670) yang bergelar La Tenri Lai To Senggeng periode Daeng Nachoda 1669 jadi latar belakang karena musnahnya Tosara ibu kota Wajo akibat serangan Spelman dan La Tenri Tatta Arung Palaka, wakhaji
Baginda Ali Belum ditemukan benang merahnya jika tahun 1653 sebagai awal masuknya armada bugis di Air Kuning catatan Datuk Haji Siraj tidak valid dari aspek analisa sejarah karena tahun 1650an Belanda belum hadir di Sulawesi. Padahal Daeng Nakhoda telah membawa peralatan perang modern hasil rampasan dari kapal Asing yg kemudian Alutista andalan kerajaan Jembrana. Ada kemungkinan Daeng Nakhoda adalah anak buah dari La Maddukkelleng yg eksodus dari Wajo ke Kalimantan abad ke XVIII. yang kemudian terdampar di Bali.
Eka Sabara 1667 sejak kejatuhan benteng somba opu ke tangan Spelman kemungkinan ade yg gaan eksodus krn daeng nachoda bersembunyi di teluk pangpang blambangan jatim
Rukidi Ganteng coba ustadz haji Damanhuri ditanya sapa tau masih simpen memories storiesnya
Baginda Ali KH. Ahmad Damanhuri, Husin Jabbar tetap mengikuti catatan Datuk Haji Siraj. Hampir seluruh perkampungan Bugis di Pesisir Nusantara yg resmi tercatat adalah abad ke XVIII
Eka Sabara Ade rujukan kuno sejarah Arya Pancoran, Jembrana hal 8 milik Gusti Ngurah Purwayadi di Negara tulisan th 1972 dan juga Babad Basang Tamiang Brangbang bahasa Bali Kuno milik Ida Bagus Gde Griya Den Kayu Mengwi dalem bentuk Lontar wakhaji
Baginda Ali Itu sebabnya patokan Suku Bugis Masuk di Jembrana kurang valid jika terjadi tahun 1653 minimal tahun 1660 an ke atas setelah perjanjian Bongaya 1667 jika ada yg masuk Bali di bawah tahun itu maka kemungkinan kapal dagang bukan Daeng Nahkoda.
Eka Sabara Dalem catetan I Wayan Reken 1972 tertulis Daeng Nachoda masuk pada tahun 1669 wakhaji sebelumnye ade yang masuk di tahun 1653 adalah Daeng Marewa singgah sebelum menuju ke Bima
Baginda Ali Apa isi tulisan G. N. Puryawadi ttg suku Bugis ? dan IBG Griya?
Rukidi Ganteng ustadz bisa cari uli berita dari bli Eka S sapa tau punya literatur lengkap
Eka Sabara Tahun yg tepat masuknye Daeng Marewa yaitu 1667 karena Daeng Marewa termasuk 4 panglima perang Keraeng Galesong IV putra Sultan Hasanuddin dari istri keempatnya. Dinyateken dalam tulisan Suryadin Laodang dalam buku Diaspora Bugis Makassar di Pulau Jawa bagian 1 dari 7 bagian
Baginda Ali Saya hubungkan dengan sejarah wajo nama Daeng Nakhoda tidak ditemukan .
Eka Sabara Baginda Ali memang disinilah misterinya karna Arya Pancoran hanya mengenal nama Nachoda kapal tsb sedangkan nama makassar atau wajo aslinya sampai saat ini belum sy dapatkan wakhaji
Eka Sabara Tentang 3 orang pembantu utama kerajaan Pancoran sewaktu raja I Gusti Arya Pancoran IV (I Gusti Ngurah Cengkrong Bang) yg 3 disebutkan Kepala Pasukan Meriam Bugis seorang Illanun ( Daeng Nachoda )
Palox Scatzhi Garis Merahkan 3 Tahapan yg menerangkan Sejarah Masukkan Muslim di Jembrana..
Terima Kasih Pak Haji Baginda Ali atas Tulisannya.. Keren..
Ngopi + megesah sejarah enak ni Bang Eka Sabara R M Fauzi.. Hehehe
Baginda Ali Jika Daeng Marewa adalah anak buah ekspedisi Karaeng Galesong ( putra sulung Sultah Hasanuddin ) masuk Bali tahun 1653 juga tidak valid karena Karaeng Galesong ekpedisi ke jawa dimulai tahun 1671 mendarat di Banten 800 laskar dg persenjataan lengkap membatu Sultan Ageng Tirtayasa menghalau armada Belanda dan berhasil tapi itu dari Gowa bukan Wajo. Sejarah Buleleng juga mengakui bahwa yg terdampar pertama di Buleleng adalah anak buah Karaeng Galesong Gowa itu Makassar bukan Bugis.
Palox Scatzhi Ada 3 Tahap sebelum datangnya Datok Syarif Tua Ke Loloan..
Menurut catatan datuk haji Mohammad Sirad bin Kalibin kampung baru (sekarang lingkungan kerobokan loloan barat) menyebutkan : bahwa perahu perahu Bugis / Makasar tipe Lambo Vinisi berdatangan di air kuning cara bertahap atau bergelombang dalam tahun yang berbeda beda. Tahun tahun kedatangannya itu sebagai berikut : pertama dalam tahun 1.1653 1655m.
2. 1660 1661m.
3 1667 1669m.
Dan ini sangat bertepatan dg bbrp kejadian di Sulawesi
1.1652 : pimpinan maluku majira dtng ke Gowa menghadap sultan M. Said
2. 1653 : Gowa bersama 5000 pasukan menuju kerajaan Buton agar bersatu
3. 1653 : Sultan Moh. Said Wafat di Ganti Hasanuddin yg waktu itu berusia 22 th..
Dalam masa singkat terjadilah ketegangan ketegangan hebat antara pihak Gowa dengan belanda VOC itu. Dan terjadilah duel meriam diperairan Sulawesi selatan ditahun itu.
Akibat pertempuran laut yang hebat dengan duel meriam terus menerus itu, maka banyak perahu diantara armada Gowa itu diuber uber kapal belanda hingga mendarat dinusa tenggara timur dan barat termasuk juga dibali, khususnya didaerah jembrana.
Eka Sabara Dalam tulisan oleh Abdul Rajak Daeng Patunru tahun 1964 berjudul Sejarah Wajo terbitan Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan juga dalam buku Sejarah Goa, Makassar terbitan sama berbeda tahun 1967 disana ada disebutkan Daeng Nachoda yg dikejar Spellman hingga bersembunyi di teluk pangpang Banyuwangi
Andi Agus Susanto Lanjutken
Baginda Ali Saya lebih setuju jika Daeng Marewa dan Daeng Nakhoda itu berasal dari Gowa bukan Wajo karena dari segi nama saja berciri suku Makassar ( Gowa ) meskipun tidak bisa dipastikan. Sebab Loloan sendiri yg tertinggal bahasanya adalah bahasa Makassar jarang diketemukan Bahasa Bugis dalam bahasa Melayu Loloan.
Di loloan tidak ada bangsawan Bugis yg bergelar Andi yg ada adalah Bangasawan Makassar yg bergelar Daeng. Itu sesimpulan saya diskusi ini menarik ...
HANYA ORANG BIJAK YANG PERHATIAN KEPADA SEJARAH NENEK MOYANGNYA Terima kasih informasi dari Mas Eka Sabara, Mas Mujtahidin, Mas Rukidi Ganteng semoga sukses dan sehar selalu amin ......
Palox Scatzhi Baginda Ali setuju..
Eka Sabara Baginda Ali mantab wakhaji...memang benar dari hasil rangkuman bnyk bahasa Makassar yg masih tersisa sebagai jejak peninggalan masa silam...Bravo literarasi yg cukup menarik.
Abha Aba Melihat foto FBL. Rindu dg loloan ( kpmpung hlmn).
Sumber : https://www.facebook.com/baginda.ali.522/posts/2136587693272405?__tn__=K-R
@ : Remaja Loloan
@ : Bang Eka Sabara https://www.facebook.com/eka.sabara?hc_ref=ARRy3WTWZOOgUKpScggliUmJEUFgOWKqi13omtsGyowuoHDtGCzn0GlgJU6fVkG3-Gc&__xts__[0]=68.ARBIOJhBYsY1AcghDy4-MzwFaa_LZVIamp5g0JIePRlT7r0XDYFmnX9a2SLv_oPWUpcROG7ul7c-Tx2Ufx4zqBTrusZLEqD58CEP1Sc7Dx4OXro_GtAj5FmRwSnY3NkKNtI7gyiljh9BNqREz6JR329nYsrMWR6meB5tkWXTxNTeu8qeRFCIeA&__tn__=lC-R
@ : https://www.facebook.com/palox.scatzhi ( Kepala Lingkungan Loloan Timur)
Editor : cikdoenk@gmail.com / https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8993475439343966765#allposts
Hal yang dirasa berat saat ini pada Entitas Kampung Islam Loloan Jembrana Bali adalah upaya mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan tradisi Nenek Moyang mereka apa lagi komunitas ini telah eksis dan berlangsung dengan rentang sejarah kurang lebih berkisar 350 tahun lalu. Suatu bentangan waktu yang tidak pendek dalam mempertahankan tradisi di suatu komunitas yang dinamis dan di tengah gelombang arus budaya asing dan era komunikasi digital yang semakin menggila. Lagi pula komunitas yang tergolong minoritas ini justeru berada di tengah-tengah kaum mayoritas di Bali. Meskipun saat ini masih ada yang tersisah dengan pasti yaitu berupa beberapa relik reliknya yang bersifat statis yang masih bisa disaksikan berupa barang-barang antik produk budaya Bugis-Makassar di abad ke XVII sedang catatan sejarahnya hanya sedikit yang terukir di atas kertas.
Catatan kuno dan kini yang ada tentang Loloan ini antara lain Manuskrip milik Datuk Haji Siraj yang ditulis dengan huruf Arab pegon tahun 1935 M, diktat yang ditulis oleh I Wayan Reken tahun 1979 M, diktat yang ditulis oleh Ust. Husin Abdul Djabbar 2010 M, adalah merupakan sumber lokal tentang komunitas yang unik di Bali ini. Adapun sumber Asing hanya ada dua antara lain buku yang ditulis oleh C. Lekkerkerker, ( Belanda ) yang berjudul Bali En Lombok, Overzicht Der Literatuur Omtrent Deze Eilanden Tot Einde, tahun 1919 M. dan buku yang ditulis oleh Williard A. Hanna ( Amerika ) yang berjudul Bali Chronicles tahun 1935.
Dalam merekontruksi bangunan sejarah komunitas Kampung Loloan yang berawal dari abad ke XVII sampai ke sini tentu lebih banyak berbasis Oral Story ( cerita dari mulut ke mulut di setiap generasi ) dari pada Wraiting Story karena sedikitnya sumber tertulis baik lokal maupun asing. Hal ini yang menjadi kemudian subyektifitasnya tidak bisa dihindarkan karena bisa jadi kontroversi keterangan satu sumber dari sumber lainya. Demikian juga para Datok moyangnya sebagai bagian dari imforman pelaku sejarah sudah banyak yang telah tiada.
Langkah lain yang harus dilakukan oleh komunitas ini adalah upaya memperkenalkan produk-produk budaya leluhurnya agar tidak menjadi generasi yang missinglink terhadap leluhurnya yang telah membentuk inclave di pulau Bali ini . Untuk itu tentu kita sangat mengapresiasi prakarsa dari Generasi Muda Loloan Jembrana ini dalam upaya melestarikan warisan Budaya dan Tradisi Pendahulunya sejak abad ke XVII dengan melaksanakan agenda tahunan Fastival Budaya Loloan yang bertema “Pentas Loloan Tempoe Doeloe”. minimal dari acara ini sebagai ajang untuk dapat memperkenalkan produk Budaya nenek moyangnya baik berupa Benda (Tangabel) maupun Non Benda ( Non Tangabel ) kepada generasi sekarang agar menjadi inpirasi dan motivasi bagi mereka dalam membangun kampung ini di masa yang akan datang agar menjadi “Generasi Idaman dan Harapan Datok”.
Pesta yang bergelap-gelapan ini benar-benar menggambarkan nuansa di masa 3,5 abad silam di mana waktu itu Kampung Loloan Jembrana dan umumnya pulau Bali masih berupa hutan belantara akses antara satu daerah dengan daerah lainnya hanya ditempuh lewat jalur laut dan perkampungan pun masih jarang untuk daerah Jembrana yang ramai hanya di seputaran kampung Loloan ini saja oleh karena di situ ada Dermaga / Pelabuhan utama Jembrana dan Pasar umum dan dikunjungi pendatang dari luar daerah sedang di tempat lainnya hamper tidak ada keramaian.
Di sisi lain bahwa Pesta Rakyat ini adalah sebagai salah satu agenda wisata budaya yang sangat mungkin untuk dikembangkan di masa mendatang. Oleh karena acara ini banyak menyimpan hal-hal unik yang bisa dikemas menjadi obyek Human Interest di Pulau Bali.
Sebagimana halnya Produk Budaya Suku Bugis-Makassar di daerah lain telah berhasil menjadikannya sebagai event pariwisata provinsi misalnya produk budaya “Mappanre tasi” ( pasta laut ) warisan budaya suku Bugis Wajo di Pagatan Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang awalnya hanya pesta rakyat lokal lalu dikemas sedemikian rupa yang akhirnya menjadi agenda wisata Kalimantan Selatan setelah Budaya Pasar terapung Banjarmasin.
Demikian pula Bahasa Melayu Loloan ( Base Loloan ) yang sudah menjadi salah satu Bahasa Daerah Nusantara tersendiri dalam rumpun Bahasa Melayu hal yang wajib hukumnya untuk dilestarikan penggunannya. Menurut Dr. Sumarsono dalam disertasinya yang telah diujikan di Universitas Indonesia 1993 yang mengangkat tema tentang “Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan” bahwa bahasa ini sangat unik keberadaannya dan yang paling utama keunikannya adalah bahwa bahasa ini bisa bertahan berabad-abad lamanya justeru di tengah pengguna bahasa Mayoritas yaitu bahasa Bali pada hal masyarakat Loloan sendiri adalah pengguna bahasa Dwilingual yang menyebabkan bahasa ini dengan penuturnya terjadi interaksi Extralingual.
Tentu juga kita perlu mengapresiasi atas prakarsa Bapak Eka Sabara yang telah bekerja sama dengan Bapak MR. Fauzi untuk menyusun Kamus BAHASA MELAYU LOLOAN – INDONESIA yang saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Kalau tidak ada upaya ini tentu Bahasa Melayu Loloan sedikit-demi sedikit akan tergerus yang akhirnya bisa menghilang tanpa bekas seperti nasibnya bahasa Melayu Ampenan Lombok yang sudah hampir punah saat ini pada hal mungkin saja komunitas mereka telah ada sebelum bahasa Melayu Loloan digunakan.
Di lanjutkan dengan diskusi.
Eka Sabara Salut ulasan yg singkat padat dan sistematik...Wakhaji
Baginda Ali bravo setelah sy coba telusuri ternyata dimasa Arung Matoa Wajo ke 23 (1658-1670) yang bergelar La Tenri Lai To Senggeng periode Daeng Nachoda 1669 jadi latar belakang karena musnahnya Tosara ibu kota Wajo akibat serangan Spelman dan La Tenri Tatta Arung Palaka, wakhaji
Rukidi Ganteng ini baru ustadz hebat
lahir d Madura buat crite sejarah di kampoeng loeloean yang artinye
muare makasih ustadz mudahan yg mude tergugah untuk membuat memories
tentang kampoeng loeloean.syukron ustadz.
Baginda Ali Belum ditemukan benang merahnya jika tahun 1653 sebagai awal masuknya armada bugis di Air Kuning catatan Datuk Haji Siraj tidak valid dari aspek analisa sejarah karena tahun 1650an Belanda belum hadir di Sulawesi. Padahal Daeng Nakhoda telah membawa peralatan perang modern hasil rampasan dari kapal Asing yg kemudian Alutista andalan kerajaan Jembrana. Ada kemungkinan Daeng Nakhoda adalah anak buah dari La Maddukkelleng yg eksodus dari Wajo ke Kalimantan abad ke XVIII. yang kemudian terdampar di Bali.
Eka Sabara 1667 sejak kejatuhan benteng somba opu ke tangan Spelman kemungkinan ade yg gaan eksodus krn daeng nachoda bersembunyi di teluk pangpang blambangan jatim
Rukidi Ganteng coba ustadz haji Damanhuri ditanya sapa tau masih simpen memories storiesnya
Baginda Ali KH. Ahmad Damanhuri, Husin Jabbar tetap mengikuti catatan Datuk Haji Siraj. Hampir seluruh perkampungan Bugis di Pesisir Nusantara yg resmi tercatat adalah abad ke XVIII
Eka Sabara Ade rujukan kuno sejarah Arya Pancoran, Jembrana hal 8 milik Gusti Ngurah Purwayadi di Negara tulisan th 1972 dan juga Babad Basang Tamiang Brangbang bahasa Bali Kuno milik Ida Bagus Gde Griya Den Kayu Mengwi dalem bentuk Lontar wakhaji
Baginda Ali Itu sebabnya patokan Suku Bugis Masuk di Jembrana kurang valid jika terjadi tahun 1653 minimal tahun 1660 an ke atas setelah perjanjian Bongaya 1667 jika ada yg masuk Bali di bawah tahun itu maka kemungkinan kapal dagang bukan Daeng Nahkoda.
Eka Sabara Dalem catetan I Wayan Reken 1972 tertulis Daeng Nachoda masuk pada tahun 1669 wakhaji sebelumnye ade yang masuk di tahun 1653 adalah Daeng Marewa singgah sebelum menuju ke Bima
Baginda Ali Apa isi tulisan G. N. Puryawadi ttg suku Bugis ? dan IBG Griya?
Rukidi Ganteng ustadz bisa cari uli berita dari bli Eka S sapa tau punya literatur lengkap
Eka Sabara Tahun yg tepat masuknye Daeng Marewa yaitu 1667 karena Daeng Marewa termasuk 4 panglima perang Keraeng Galesong IV putra Sultan Hasanuddin dari istri keempatnya. Dinyateken dalam tulisan Suryadin Laodang dalam buku Diaspora Bugis Makassar di Pulau Jawa bagian 1 dari 7 bagian
Baginda Ali Saya hubungkan dengan sejarah wajo nama Daeng Nakhoda tidak ditemukan .
Eka Sabara Baginda Ali memang disinilah misterinya karna Arya Pancoran hanya mengenal nama Nachoda kapal tsb sedangkan nama makassar atau wajo aslinya sampai saat ini belum sy dapatkan wakhaji
Eka Sabara Tentang 3 orang pembantu utama kerajaan Pancoran sewaktu raja I Gusti Arya Pancoran IV (I Gusti Ngurah Cengkrong Bang) yg 3 disebutkan Kepala Pasukan Meriam Bugis seorang Illanun ( Daeng Nachoda )
Palox Scatzhi Garis Merahkan 3 Tahapan yg menerangkan Sejarah Masukkan Muslim di Jembrana..
Terima Kasih Pak Haji Baginda Ali atas Tulisannya.. Keren..
Ngopi + megesah sejarah enak ni Bang Eka Sabara R M Fauzi.. Hehehe
Baginda Ali Jika Daeng Marewa adalah anak buah ekspedisi Karaeng Galesong ( putra sulung Sultah Hasanuddin ) masuk Bali tahun 1653 juga tidak valid karena Karaeng Galesong ekpedisi ke jawa dimulai tahun 1671 mendarat di Banten 800 laskar dg persenjataan lengkap membatu Sultan Ageng Tirtayasa menghalau armada Belanda dan berhasil tapi itu dari Gowa bukan Wajo. Sejarah Buleleng juga mengakui bahwa yg terdampar pertama di Buleleng adalah anak buah Karaeng Galesong Gowa itu Makassar bukan Bugis.
Palox Scatzhi Ada 3 Tahap sebelum datangnya Datok Syarif Tua Ke Loloan..
Menurut catatan datuk haji Mohammad Sirad bin Kalibin kampung baru (sekarang lingkungan kerobokan loloan barat) menyebutkan : bahwa perahu perahu Bugis / Makasar tipe Lambo Vinisi berdatangan di air kuning cara bertahap atau bergelombang dalam tahun yang berbeda beda. Tahun tahun kedatangannya itu sebagai berikut : pertama dalam tahun 1.1653 1655m.
2. 1660 1661m.
3 1667 1669m.
Dan ini sangat bertepatan dg bbrp kejadian di Sulawesi
1.1652 : pimpinan maluku majira dtng ke Gowa menghadap sultan M. Said
2. 1653 : Gowa bersama 5000 pasukan menuju kerajaan Buton agar bersatu
3. 1653 : Sultan Moh. Said Wafat di Ganti Hasanuddin yg waktu itu berusia 22 th..
Dalam masa singkat terjadilah ketegangan ketegangan hebat antara pihak Gowa dengan belanda VOC itu. Dan terjadilah duel meriam diperairan Sulawesi selatan ditahun itu.
Akibat pertempuran laut yang hebat dengan duel meriam terus menerus itu, maka banyak perahu diantara armada Gowa itu diuber uber kapal belanda hingga mendarat dinusa tenggara timur dan barat termasuk juga dibali, khususnya didaerah jembrana.
Eka Sabara Dalam tulisan oleh Abdul Rajak Daeng Patunru tahun 1964 berjudul Sejarah Wajo terbitan Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan juga dalam buku Sejarah Goa, Makassar terbitan sama berbeda tahun 1967 disana ada disebutkan Daeng Nachoda yg dikejar Spellman hingga bersembunyi di teluk pangpang Banyuwangi
Andi Agus Susanto Lanjutken
Baginda Ali Saya lebih setuju jika Daeng Marewa dan Daeng Nakhoda itu berasal dari Gowa bukan Wajo karena dari segi nama saja berciri suku Makassar ( Gowa ) meskipun tidak bisa dipastikan. Sebab Loloan sendiri yg tertinggal bahasanya adalah bahasa Makassar jarang diketemukan Bahasa Bugis dalam bahasa Melayu Loloan.
Di loloan tidak ada bangsawan Bugis yg bergelar Andi yg ada adalah Bangasawan Makassar yg bergelar Daeng. Itu sesimpulan saya diskusi ini menarik ...
HANYA ORANG BIJAK YANG PERHATIAN KEPADA SEJARAH NENEK MOYANGNYA Terima kasih informasi dari Mas Eka Sabara, Mas Mujtahidin, Mas Rukidi Ganteng semoga sukses dan sehar selalu amin ......
Palox Scatzhi Baginda Ali setuju..
Eka Sabara Baginda Ali mantab wakhaji...memang benar dari hasil rangkuman bnyk bahasa Makassar yg masih tersisa sebagai jejak peninggalan masa silam...Bravo literarasi yg cukup menarik.
Abha Aba Melihat foto FBL. Rindu dg loloan ( kpmpung hlmn).
Sumber : https://www.facebook.com/baginda.ali.522/posts/2136587693272405?__tn__=K-R
@ : Remaja Loloan
@ : Bang Eka Sabara https://www.facebook.com/eka.sabara?hc_ref=ARRy3WTWZOOgUKpScggliUmJEUFgOWKqi13omtsGyowuoHDtGCzn0GlgJU6fVkG3-Gc&__xts__[0]=68.ARBIOJhBYsY1AcghDy4-MzwFaa_LZVIamp5g0JIePRlT7r0XDYFmnX9a2SLv_oPWUpcROG7ul7c-Tx2Ufx4zqBTrusZLEqD58CEP1Sc7Dx4OXro_GtAj5FmRwSnY3NkKNtI7gyiljh9BNqREz6JR329nYsrMWR6meB5tkWXTxNTeu8qeRFCIeA&__tn__=lC-R
@ : https://www.facebook.com/palox.scatzhi ( Kepala Lingkungan Loloan Timur)
Editor : cikdoenk@gmail.com / https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8993475439343966765#allposts
Rabu, 29 Agustus 2018
KH. AHMAD DAHLAN TERMAS
"KH Ahmad Dahlan" Bukan Pendiri Muhammadiyah, Tapi Ahli Falak
Oleh M. Rikza Chamami
DutaIslam.Com - Salah satu ulama Nusantara yang dikenal ahli dalam bidang ilmu falak adalah KH Ahmad Dahlan yang lahir di Termas Pacitan Jawa Timur 1862 dan wafat di Semarang 1911. Makam KH Ahmad Dahlan berada di sisi timur Makam KH Sholeh Darat di Makam Bergota Semarang. Menyebut nama Ahmad Dahlan memang orang menjadi tertuju pada sosok pendiri Muhammadiyah. Dan ternyata dua sosok bernama yang sama itu, KH Ahmad Dahlan Termas dan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta, sama-sama mengaji di Pondok Pesantren KH Sholeh Darat.
KH Ahmad Dahlan Termas (sebagian orang menyebut KH Ahmad Dahlan
Semarang) merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Mannan bin Demang
Dipomenggolo I yang merupakan keturunan Ketok Jenggot punggawa Keraton
Surakarta, tokoh cikal bakal berdirinya daerah Termas. Dipomenggolo I
merupakan seorang santri ahli agama yang berdarah bangsawan yang
mendirikan Pesantren Semanten. Salah satu putra Dipomenggolo bernama Mas
Bagus Sudarso juga dikirim belajar agama di Pondok Pesantren Tegalsari
Ponorogo. Di pesantren yang juga mengkaji budaya ini diasuh Bagus Burhan
atau Ronggowarsito.
Kakak dari KH Ahmad Dahlan adalah KH Mahfudz Termas (1842-1920) dan adiknya bernama KH Dimyati Termas (wafat 1934). Tiga bersaudara ini memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Dunia pesantren sangat mengakui peran besar kakak-beradik ini dalam keilmuan-keilmuan agama Islam terutama paham ahlussunnah wal jama’ah.
Sehingga sosok KH Ahmad Dahlan yang sangat pandai tidak bisa dilepaskan dari kiprah keluarganya. Keluarga Termas memang sudah dikenal melahirkan ulama Nusantara yang sangat berkontribusi besar dalam dunia pesantren. Misalnya KH Mahfudz Termas dikenal sebagai ulama yang memiliki puluhan karya kitab dan spesialis di bidang hadits, telah mencetak murid yang menjadi ulama pesantren.
Keahlian KH Ahmad Dahlan Termas dalam bidang ilmu falak ditandai dengan penyebutan namanya dengan sebutan KH Ahmad Dahlan Alfalaky. Kepandaiannya dalam ilmu agama, menjadikannya diambil sebagai menantu KH Sholeh Darat. Ia dinikahkan dengan putri KH Sholeh Darat bernama RA Siti Zahra dari jalur istri RA Siti Aminah binti Sayyid Ali. Dari pernikahan ini, pada tahun 1895, melahirkan anak bernama Raden Ahmad Al Hadi yang kelak ketika dewasa menjadi tokoh Islam di Jembrana Bali.
KH Ahmad Dahlan memulai pendidikannya dari para Kyai yang ada di Termas kemudian melanjutkan belajar kepada kakaknya KH Mahfudz Termas yang ada di Makkah. Saat di tanah suci inilah KH Ahmad Dahlan bersahabat dengan ahli falak Syaikh Muhammad Hasan Asy’ari Bawean Madura (wafat 1921). Syaikh Muhammad Hasan Asy’ari mempunyai karya Kitab Muntaha Nataiji al Aqwal.
Dalam buku Materpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri 1320-1945 karya Zainul Milal Bizawie disebutkan bahwa KH Ahmad Dahlan dan Syaikh Muhammad Hasan Asy’ari berangkat menuju beberapa wilayah Arab dan menuju ke Al Azhar Kairo. Di Kairo keduanya berjumpa dengan dua ulama Nusantara: Syaikh Jamil Djambek dan Syaikh Ahmad Thahir Jalaludin. Selama di Kairo, keduanya mengkhatamkan kitab induk ilmu falak karya Syaikh Husain Zaid Al Mishri, Al Mathla’ fi Al Sa’id fi Hisabi al Kawakib ‘ala Rashdi al Jadid yang ditulis awal abad 19.
Setelah selesai belajar di Arab, kemudian ia pulang ke tanah air. Berdasarkan saran dari kakaknya, sesampai di tanah air KH Ahmad Dahlan bersama dengan Syaikh Hasan Asy’ari diminta untuk belajar agama dengan KH Sholeh Darat di Semarang. Maka pesan itu dilaksanakan. KH Ahmad Dahlan mengaji dengan KH Sholeh Darat di Semarang. Dan sudah menjadi tradisi para ulama Nusantara, para santri yang sudah belajar di Arab tetap diminta belajar di Indonesia lagi, terutama dengan KH Sholeh Darat atau KH Cholil Bangkalan.
Karya-karya di bidang Falak yang dilahirkan oleh KH Ahmad Dahlan adalah: Tadzkiratu al Ikhwan fi Ba’dli Tawarikhi wal ‘Amali al Falakiyati (selesai ditulis 1901), Natijah al Miqat (selesai ditulis 1903) dan Bulughu al Wathar (selesai ditulis 27 Dzul Qa’dah 1320 di Darat Semarang). Ditengarai, masih banyak karya-karya KH Ahmad Dahlan yang sampai sekarang belum terlacak.
Dalam Kitab Tadzkiratu al Ikhwan fi Ba’dli Tawarikhi wal ‘Amali al Falakiyati ditegaskan oleh Zainul Milal Bizawie sebagai kitab hisab awal bulan pertama yang ditulis oleh ulama Nusantara. Ini menjawab atas dugaan selama ini bahwa kitab hisab awal bulan yang pertama ditulis adalah Sullam Nayyirin yang baru ditulis 1925. Pola kitab karya KH Ahmad Dahlan masih menggunakan angka Abajadun dengan memakai Zaij Ulugh Beik.
Kitab Natijah al Miqat berisi tentang kaidah ilmu falak tentang penggunaan rubu’ mujayyab dalam penentuan awal waktu shalat dan arah kiblat. Dalam kitab ini juga dirangkumkan pemikiran-pemikiran guru KH Ahmad Dahlan: Syaikh Husain Zaid Mesir, Syaikh Abdurrahman bin Ahmad Mesir, Syaikh Muhammad bin Yusuf Makkah dan KH Sholeh Darat. Kemudian pada tahun 1930, kitab Natijah al Miqat disyarahi oleh Syaikh Ihsan Jampes (wafat 1952) dengan kitabnya Tashrihu al Ibarat.
Kitab Bulughu al Wathar ini merupakan kitab falak pertama yang ditulis ulama Nusantara dengan sistem haqiqi tahqiqi. Kitab ini selesai ditulis bersamaan dengan kitab Muntaha Nataij al Aqwal karya Syaikh Hasan Asy’ari Bawean. Induk kitab yang dirujuk dalam membuat Bulughu al Wathar dan Muntaha Nataij al Aqwal berasal dari ilmu zaij Kitab Al Mathla’ fi Al Sa’id fi Hisabi al Kawakib ‘ala Rashdi al Jadid karya Syaikh Husain Zaid Al Mishri.
Khazanah keilmuan falak yang dimiliki oleh KH Ahmad Dahlan dan Syaikh Hasan Asy’ari Bawean ini yang turut serta mewarnai perkembangan ilmu falak di Pondok Pesantren. Dinamika keilmuan falak di dunia pesantren selalu merujuk pada kajian-kajian ilmiah ulama Nusantara yang mampu mengembangkan ilmu falak yang berasal dari Arab.
KH Ahmad Dahlan dalam kesehariannya, bersama keluarga menempati rumah di sekitar Masjid Agung Kauman Semarang. KH Ahmad Dahlan selain dikenal sebagai ulama, juga ahli dalam bidang dagang dan tergolong berekonomi kuat (punya banyak toko di Pasar Johar). Bekal itulah yang digunakan untuk berjuang membangun dakwah Islam di Kota Semarang. Dan sepeninggal KH Sholeh Darat pada tahun 18 Desember 1903, Pondok Pesantren Darat diasuh oleh KH Ahmad Dahlan.
Selama kurang lebih delapan tahun, KH Ahmad Dahlan menggantikan guru sekaligus mertuanya mendidik para santri yang belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Darat. Dengan segala dedikasi penuh, para santri yang mengaji di Pondok tersebut diajar sebagaimana cara KH Sholeh Darat mendidik. Termasuk KH Ahmad Dahlan mengajarkan ilmu falak kepada para santri-santrinya dengan menggunakan tiga kitab falak yang ditulisnya.
Keahlian ilmu falak yang dimiliki oleh KH Ahmad Dahlan tidak pernah lepas dari keahlian falak yang dimiliki oleh KH Sholeh Darat. Dalam beberapa kisah disebutkan bahwa KH Sholeh Darat yang merupakan guru dari ulama Jawa ini sangat tepat dalam menghitung waktu shalat dan penentuan awal bulan Ramadan dan Syawwal.
Proses penegasan dalam penentuan waktu shalat dan Ramadan ia tegaskan dalam beberapa karyanya. Termasuk keterbukaan KH Sholeh Darat dalam mengawal tradisi “Dugderan” di Kota Semarang sebagai bentuk kepedulian ilmu falak dan ilmu sosial. Dimana ketika masyarakat Semarang ingin menyambut kehadiran Ramadan dirayakan dengan bunyi-bunyi bedug dan petasan, maka disebut dug der (dug bunyi bedug dan der bunyi petasan).
Keahlian falak yang dimiliki KH Sholeh Darat adalah ketika diminta menghitung jumlah palawija yang ada di dalam karung oleh Belanda. Dengan sangat cepat berdasar ilmu hitung falaknya, maka KH Sholeh Darat memberikan jawaban dengan tepat. Kekaguman Belanda pada prediksi jumlah isi palawija itulah yang menjadikan Belanda kagum dengan ilmu falak KH Sholeh Darat.
Putra KH Ahmad Dahlan yang bernama Raden Ahmad Al Hadi berdakwah menuju Loloan Timur Jembrana Bali adalah karena mendapatkan isyarat dari KH Cholil Bangkalan (1820-1925) selaku gurunya. Selain itu, setelah KH Ahmad Dahlan wafat, Ibunya menikah lagi dengan KH Amir dan pindah ke Simbang Kulon Pekalongan. Dengan bekal ilmu agama yang dimiliki itu, putra KH Ahmad Dahlan bernama Ahmad ini berdakwah ke Bali.
Sebagaimana ayahnya, Raden Ahmad Al Hadi sangat senang dengan ilmu pengetahuan agama. Walaupun sejak kecil sudah dilatih berdagang di Pasar Johar Semarang, namun Raden Ahmad Al Hadi tetap semangat mengaji. Sehingga di usia 16 tahun ketika ia ditinggal wafat KH Ahmad Dahlan ia ikut belajar di Pondok Pesantren ayah tirinya, KH Amir. Setelah itu ia merantau dari pondok ke pondok hingga pernah belajar Makkah.
Sebagaimana dijelaskan oleh KH Fathur RA (anak kandung Raden Ahmad bin Ahmad Dahlan), bahwa Raden Ahmad sangat tinggi minat belajarnya. Pondok Pesantren yang dijadikan tempat mencari ilmu adalah: Pondok Pesantren Kaliwungu (berteman dengan KH Abul Choir selama dua tahun), Pondok Pesantren Buntet Cirebon (belajar ilmu silat), Pondok Pesantren Kyai Umar Sarang (belajar ilmu alat), Pondok Pesantren KH Munawwir Krapyak Yogyakarta (belajar Al Qur’an), Pondok Pesantren KH Dimyati Termas, Pondok Pesantren KH Idris Jamsaren Solo.
Setelah tamat dari Pondok Manbaul Ulum Jamsaren Solo dengan bekal Beslit dari Governoor Belanda Jawa Tengah, Raden Ahmad melanjutkan belajar ke Makkah dan Madinah berguru dengan pamannya sendiri, KH Mahfudz Termas.
Sepulang dari Arab, Raden Ahmad masih mengaji dengan KH M Hasyim Asy’ari di Jombang (satu tahun) dan KH Cholil Bangkalan Madura (satu tahun). Saat di Bangkalan inilah ia bertemu dengan KH Kusairi Shiddiq (mertua KH Abdul Hamid Pasuruan). Perintah Kyai Cholil pada Raden Ahmad adalah menuju Bali bertemu dengan murid Kyai Cholil yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad di Loloan Timur Jembrana Bali. Dan ia jalani hingga mendirikan Pondok Pesantren Manba’ul Ulum di Jembrana Bali. Nama “Manba’ul Ulum “ adalah tabarrukan dengan almamaternya saat mondok di Jamsaren. Wallahu a’lam. [dutaislam.com/ ab]
DutaIslam.Com - Salah satu ulama Nusantara yang dikenal ahli dalam bidang ilmu falak adalah KH Ahmad Dahlan yang lahir di Termas Pacitan Jawa Timur 1862 dan wafat di Semarang 1911. Makam KH Ahmad Dahlan berada di sisi timur Makam KH Sholeh Darat di Makam Bergota Semarang. Menyebut nama Ahmad Dahlan memang orang menjadi tertuju pada sosok pendiri Muhammadiyah. Dan ternyata dua sosok bernama yang sama itu, KH Ahmad Dahlan Termas dan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta, sama-sama mengaji di Pondok Pesantren KH Sholeh Darat.
Kakak dari KH Ahmad Dahlan adalah KH Mahfudz Termas (1842-1920) dan adiknya bernama KH Dimyati Termas (wafat 1934). Tiga bersaudara ini memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Dunia pesantren sangat mengakui peran besar kakak-beradik ini dalam keilmuan-keilmuan agama Islam terutama paham ahlussunnah wal jama’ah.
Sehingga sosok KH Ahmad Dahlan yang sangat pandai tidak bisa dilepaskan dari kiprah keluarganya. Keluarga Termas memang sudah dikenal melahirkan ulama Nusantara yang sangat berkontribusi besar dalam dunia pesantren. Misalnya KH Mahfudz Termas dikenal sebagai ulama yang memiliki puluhan karya kitab dan spesialis di bidang hadits, telah mencetak murid yang menjadi ulama pesantren.
Keahlian KH Ahmad Dahlan Termas dalam bidang ilmu falak ditandai dengan penyebutan namanya dengan sebutan KH Ahmad Dahlan Alfalaky. Kepandaiannya dalam ilmu agama, menjadikannya diambil sebagai menantu KH Sholeh Darat. Ia dinikahkan dengan putri KH Sholeh Darat bernama RA Siti Zahra dari jalur istri RA Siti Aminah binti Sayyid Ali. Dari pernikahan ini, pada tahun 1895, melahirkan anak bernama Raden Ahmad Al Hadi yang kelak ketika dewasa menjadi tokoh Islam di Jembrana Bali.
KH Ahmad Dahlan memulai pendidikannya dari para Kyai yang ada di Termas kemudian melanjutkan belajar kepada kakaknya KH Mahfudz Termas yang ada di Makkah. Saat di tanah suci inilah KH Ahmad Dahlan bersahabat dengan ahli falak Syaikh Muhammad Hasan Asy’ari Bawean Madura (wafat 1921). Syaikh Muhammad Hasan Asy’ari mempunyai karya Kitab Muntaha Nataiji al Aqwal.
Dalam buku Materpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri 1320-1945 karya Zainul Milal Bizawie disebutkan bahwa KH Ahmad Dahlan dan Syaikh Muhammad Hasan Asy’ari berangkat menuju beberapa wilayah Arab dan menuju ke Al Azhar Kairo. Di Kairo keduanya berjumpa dengan dua ulama Nusantara: Syaikh Jamil Djambek dan Syaikh Ahmad Thahir Jalaludin. Selama di Kairo, keduanya mengkhatamkan kitab induk ilmu falak karya Syaikh Husain Zaid Al Mishri, Al Mathla’ fi Al Sa’id fi Hisabi al Kawakib ‘ala Rashdi al Jadid yang ditulis awal abad 19.
Setelah selesai belajar di Arab, kemudian ia pulang ke tanah air. Berdasarkan saran dari kakaknya, sesampai di tanah air KH Ahmad Dahlan bersama dengan Syaikh Hasan Asy’ari diminta untuk belajar agama dengan KH Sholeh Darat di Semarang. Maka pesan itu dilaksanakan. KH Ahmad Dahlan mengaji dengan KH Sholeh Darat di Semarang. Dan sudah menjadi tradisi para ulama Nusantara, para santri yang sudah belajar di Arab tetap diminta belajar di Indonesia lagi, terutama dengan KH Sholeh Darat atau KH Cholil Bangkalan.
Karya-karya di bidang Falak yang dilahirkan oleh KH Ahmad Dahlan adalah: Tadzkiratu al Ikhwan fi Ba’dli Tawarikhi wal ‘Amali al Falakiyati (selesai ditulis 1901), Natijah al Miqat (selesai ditulis 1903) dan Bulughu al Wathar (selesai ditulis 27 Dzul Qa’dah 1320 di Darat Semarang). Ditengarai, masih banyak karya-karya KH Ahmad Dahlan yang sampai sekarang belum terlacak.
Dalam Kitab Tadzkiratu al Ikhwan fi Ba’dli Tawarikhi wal ‘Amali al Falakiyati ditegaskan oleh Zainul Milal Bizawie sebagai kitab hisab awal bulan pertama yang ditulis oleh ulama Nusantara. Ini menjawab atas dugaan selama ini bahwa kitab hisab awal bulan yang pertama ditulis adalah Sullam Nayyirin yang baru ditulis 1925. Pola kitab karya KH Ahmad Dahlan masih menggunakan angka Abajadun dengan memakai Zaij Ulugh Beik.
Kitab Natijah al Miqat berisi tentang kaidah ilmu falak tentang penggunaan rubu’ mujayyab dalam penentuan awal waktu shalat dan arah kiblat. Dalam kitab ini juga dirangkumkan pemikiran-pemikiran guru KH Ahmad Dahlan: Syaikh Husain Zaid Mesir, Syaikh Abdurrahman bin Ahmad Mesir, Syaikh Muhammad bin Yusuf Makkah dan KH Sholeh Darat. Kemudian pada tahun 1930, kitab Natijah al Miqat disyarahi oleh Syaikh Ihsan Jampes (wafat 1952) dengan kitabnya Tashrihu al Ibarat.
Kitab Bulughu al Wathar ini merupakan kitab falak pertama yang ditulis ulama Nusantara dengan sistem haqiqi tahqiqi. Kitab ini selesai ditulis bersamaan dengan kitab Muntaha Nataij al Aqwal karya Syaikh Hasan Asy’ari Bawean. Induk kitab yang dirujuk dalam membuat Bulughu al Wathar dan Muntaha Nataij al Aqwal berasal dari ilmu zaij Kitab Al Mathla’ fi Al Sa’id fi Hisabi al Kawakib ‘ala Rashdi al Jadid karya Syaikh Husain Zaid Al Mishri.
Khazanah keilmuan falak yang dimiliki oleh KH Ahmad Dahlan dan Syaikh Hasan Asy’ari Bawean ini yang turut serta mewarnai perkembangan ilmu falak di Pondok Pesantren. Dinamika keilmuan falak di dunia pesantren selalu merujuk pada kajian-kajian ilmiah ulama Nusantara yang mampu mengembangkan ilmu falak yang berasal dari Arab.
KH Ahmad Dahlan dalam kesehariannya, bersama keluarga menempati rumah di sekitar Masjid Agung Kauman Semarang. KH Ahmad Dahlan selain dikenal sebagai ulama, juga ahli dalam bidang dagang dan tergolong berekonomi kuat (punya banyak toko di Pasar Johar). Bekal itulah yang digunakan untuk berjuang membangun dakwah Islam di Kota Semarang. Dan sepeninggal KH Sholeh Darat pada tahun 18 Desember 1903, Pondok Pesantren Darat diasuh oleh KH Ahmad Dahlan.
Selama kurang lebih delapan tahun, KH Ahmad Dahlan menggantikan guru sekaligus mertuanya mendidik para santri yang belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Darat. Dengan segala dedikasi penuh, para santri yang mengaji di Pondok tersebut diajar sebagaimana cara KH Sholeh Darat mendidik. Termasuk KH Ahmad Dahlan mengajarkan ilmu falak kepada para santri-santrinya dengan menggunakan tiga kitab falak yang ditulisnya.
Keahlian ilmu falak yang dimiliki oleh KH Ahmad Dahlan tidak pernah lepas dari keahlian falak yang dimiliki oleh KH Sholeh Darat. Dalam beberapa kisah disebutkan bahwa KH Sholeh Darat yang merupakan guru dari ulama Jawa ini sangat tepat dalam menghitung waktu shalat dan penentuan awal bulan Ramadan dan Syawwal.
Proses penegasan dalam penentuan waktu shalat dan Ramadan ia tegaskan dalam beberapa karyanya. Termasuk keterbukaan KH Sholeh Darat dalam mengawal tradisi “Dugderan” di Kota Semarang sebagai bentuk kepedulian ilmu falak dan ilmu sosial. Dimana ketika masyarakat Semarang ingin menyambut kehadiran Ramadan dirayakan dengan bunyi-bunyi bedug dan petasan, maka disebut dug der (dug bunyi bedug dan der bunyi petasan).
Keahlian falak yang dimiliki KH Sholeh Darat adalah ketika diminta menghitung jumlah palawija yang ada di dalam karung oleh Belanda. Dengan sangat cepat berdasar ilmu hitung falaknya, maka KH Sholeh Darat memberikan jawaban dengan tepat. Kekaguman Belanda pada prediksi jumlah isi palawija itulah yang menjadikan Belanda kagum dengan ilmu falak KH Sholeh Darat.
Putra KH Ahmad Dahlan yang bernama Raden Ahmad Al Hadi berdakwah menuju Loloan Timur Jembrana Bali adalah karena mendapatkan isyarat dari KH Cholil Bangkalan (1820-1925) selaku gurunya. Selain itu, setelah KH Ahmad Dahlan wafat, Ibunya menikah lagi dengan KH Amir dan pindah ke Simbang Kulon Pekalongan. Dengan bekal ilmu agama yang dimiliki itu, putra KH Ahmad Dahlan bernama Ahmad ini berdakwah ke Bali.
Sebagaimana ayahnya, Raden Ahmad Al Hadi sangat senang dengan ilmu pengetahuan agama. Walaupun sejak kecil sudah dilatih berdagang di Pasar Johar Semarang, namun Raden Ahmad Al Hadi tetap semangat mengaji. Sehingga di usia 16 tahun ketika ia ditinggal wafat KH Ahmad Dahlan ia ikut belajar di Pondok Pesantren ayah tirinya, KH Amir. Setelah itu ia merantau dari pondok ke pondok hingga pernah belajar Makkah.
Sebagaimana dijelaskan oleh KH Fathur RA (anak kandung Raden Ahmad bin Ahmad Dahlan), bahwa Raden Ahmad sangat tinggi minat belajarnya. Pondok Pesantren yang dijadikan tempat mencari ilmu adalah: Pondok Pesantren Kaliwungu (berteman dengan KH Abul Choir selama dua tahun), Pondok Pesantren Buntet Cirebon (belajar ilmu silat), Pondok Pesantren Kyai Umar Sarang (belajar ilmu alat), Pondok Pesantren KH Munawwir Krapyak Yogyakarta (belajar Al Qur’an), Pondok Pesantren KH Dimyati Termas, Pondok Pesantren KH Idris Jamsaren Solo.
Setelah tamat dari Pondok Manbaul Ulum Jamsaren Solo dengan bekal Beslit dari Governoor Belanda Jawa Tengah, Raden Ahmad melanjutkan belajar ke Makkah dan Madinah berguru dengan pamannya sendiri, KH Mahfudz Termas.
Sepulang dari Arab, Raden Ahmad masih mengaji dengan KH M Hasyim Asy’ari di Jombang (satu tahun) dan KH Cholil Bangkalan Madura (satu tahun). Saat di Bangkalan inilah ia bertemu dengan KH Kusairi Shiddiq (mertua KH Abdul Hamid Pasuruan). Perintah Kyai Cholil pada Raden Ahmad adalah menuju Bali bertemu dengan murid Kyai Cholil yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad di Loloan Timur Jembrana Bali. Dan ia jalani hingga mendirikan Pondok Pesantren Manba’ul Ulum di Jembrana Bali. Nama “Manba’ul Ulum “ adalah tabarrukan dengan almamaternya saat mondok di Jamsaren. Wallahu a’lam. [dutaislam.com/ ab]
M. Rikza Chamami,
Sekretaris Lakpesdam NU Kota Semarang dan Dosen UIN Walisongo
Rabu, 09 Januari 2013
SYARIF ABDULLAH BIN YAHYA AL QODRI (SYARIF TUA) TOKOH PENDIRI KAMPUNG LOLOAN JEMBRANA 1799 – 1858
TOKOH PENDIRI KAMPUNG LOLOAN JEMBRANA
1799 – 1858
I Made Sumarja
ABSTRACT
Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri (The Old Syarif) is a figure from
Pontianak, who was very opposing to the Dutch government colonial. Since
the signing of cooperative work between the Dutch and Sultan Pontianak
on 5 July 1779, the Old Syarif rebelled and he escaped to Jembrana in
the west of Bali. On his arrival in Jembrana, the Old Syarif and his
followers approached the king of Jembrana. They were well accepted by
the King and they were even given a place for their settlement in around
of river Ijo, which later this place is called Kampung Loloan. Since
then the Old Syarif gave support to Jembrana kingdom, as well as in the
politics, economics and spreading of Islam religion. The Old Syarif was
very wise and helpful, so as a figure in Kampung Loloan he was very
admired by society.
Keyword: Biography - History Figure
A. PENDAHULUAN
Menulis biografi seorang tokoh, sejak dahulu dirasakan penting
manfaatnya. Biografi berarti kumpulan informasi mengenai kehidupan dan
kegiatan tokoh dari berbagai bidang yang dianggap penting dan memegang
peranan di dalam proses pembangunan masyarakat di suatu wilayah.
Biografi dari salah satu tokoh yang telah mendahului kita perlu ditulis
karena beliau telah mengorbankan jiwa raganya untuk generasi sesudah
beliau. Mungkin generasi sekarang masih mengenal beliau, namun generasi
sesudah kita mungkin tidak mengenal lagi. Makin lama makin kabur jasa
beliau dalam ingatan generasi-generasi sesudah kita dan akhirnya mereka
akan melupakannya. Jika itu terjadi, alangkah sayangnya. Melupakan
seseorang yang telah berbuat baik bagi kita merupakan sesuatu yang
menunjukkan kekurangan dalam sikap baik kita jika tidak mau mengatakan
kekurangan dalam moral kita. Sebagai bangsa yang baik kita harus
mengenal terima kasih, harus tidak melupakannya, harus tetap
mengenangnya karena beliau sebagai cermin kehidupan baik kita. Semuanya
itu merupakan kewajiban kita sebagai penghormatan kepadanya
(Soebantardjo, 1983: 31).
Tokoh sejarah juga mempunyai arti dan nilai penting bagi kehidupan
bangsa dan negara. Perlu dikenal dan dihayati nilai-nilai pengabdiannya,
inovasi, responsivitas, kepemimpinan, sikap keterbukaan, kreativitas,
kewibawaan, dan integritas kepribadian dalam pembangunan bidang sosial,
dan budaya bangsa. Dengan penulisan biografi Syarif Abdullah Bin Yahya
Al Qodri (Syarif Tua) diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan
pengetahuan masyarakat dalam rangka pembangunan mental bangsa, pembinaan
persatuan bangsa, dan membangkitkan kebanggaan nasional.
B. KEADAAN HISTORIS JEMBRANA
Daerah Jembrana pada mulanya hanyalah merupakan hutan belantara dari
ujung timur wilayahnya sampai ujung barat dan banyak dihuni oleh
binatang buas, sehingga tidak seorangpun manusia yang berani masuk ke
daerah itu apalagi sampai tinggal menetap di sana. Perkembangan
selanjutnya datanglah orang-orang buangan yang berasal dari Bali timur
dan orang yang melakukan migrasi ke daerah Jembrana dengan tujuan untuk
mempertahankan hidupnya di daerah yang baru dengan bekerja keras. Selain
itu ada juga masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa. Mereka pada
umumnya mengembil tempat pemukiman di daerah pesisir pantai karena
sebagian besar mata pencaharian mereka adalah hidup sebagai nelayan.
Sedangkan para migran yang datang dari Bali timur pada umumnya hidup
dengan mata pencaharian sebagai petani baik kebun maupun sawah
(Puspawati, 1990: 25-27).
Asal-usul dari daerah Jembrana erat kaitannya dengan nama Jambu Ratna
dan Jaran Rana. Kedua nama ini masing-masing mempunyai kisah tersendiri.
Nama Jembrana erat kaitannya dengan nama sebuah istana (puri) yang
dibangun oleh I Gusti Ngurah Jembrana, keturunan I Gusti Agung Nyoman
Alangkajeng (Raja Mengwi III). I Gusti Ngurah Jembrana pergi ke Bali
barat yang terletak di ujung barat Pulau Bali, diikuti oleh kakeknya
yang bernama I Gusti Kaler, pendeta Ida Pedanda Gde Megati dan Ida
Pedanda Gde Mambal, I Gusti Ngurah Made Yasa serta diikuti oleh 400
rakyatnya. Setelah tiba di wilayah Bali barat, di daerah ini mereka
kemudian membangun sebuah istana (puri). Kebetulan di sebelah barat
istana yang di bangun terdapat pohon Jambu yang bernama Jambu Ratna.
Selesai istana dibangun, kemudian diberi nama Puri Gede Jembrana dan
daerah tempat istana dibangun dinamakan Jambu Rana kemudian disebut
Jembrana. Ada juga yang menyebutkan bahwa Jembrana berasal dari nama
seekor kuda yang bernama Jaran Rana. Istilah Jaran Rana ini erat
kaitannya dengan terjadinya peperangan antara Pecangakan dengan Bakungan
yang berawal dengan kuda yang bernama Jaran Rana (Buda, 1990: 21-23).
Diangkatnya Gajah Mada menjadi Maha Patih di Majapahit oleh Prabhu
Wisnuwardana tahun 1331 M, maka ketika itu Gajah Mada mengucapkan
sumpahnya di hadapan para bangsawan, bahwa beliau tiada akan makan
“Palapa” (rempah-rempah) sebelum seluruh kepulauan Nusantara dapat
dikuasainya atau dipersatukan di bawah Kerajaan Majapahit. Pada waktu
itu Bali Aga masih merdeka penuh, dan Raja Majapahit kurang senang
mendengar perbuatan Dalem Bedahulu (Bedulu) yang disangka menentang atau
merusak agama di Bali dan tidak mau takluk kepada Majapahit. Alasan
inilah yang dipakai untuk menaklukkan Bali (Nyoka, 1990: 3).
Bali mengalami perubahan setelah diambil alih dari tangan Dalem Bedahulu
yang bergelar Sri Astasura Ratna Bhumi Banten (Raja Bali) oleh Patih
Gajah Mada dari Majapahit pada tahun 1343 M. Keadaan Pulau Bali
bertahun-tahun masih penuh kekacauan dan terjadi pembrontakan di
sana-sini. Masih banyak juga orang-orang yang tidak mau tunduk kepada
majapahit. Untuk mengatasi hal ini Patih Gajah Mada mohon kepada
Dhanghyang Kepakisan agar beliau berkenan memberikan seorang putranya
untuk diangkat menjadi Adipati di Bali. Beliau memberikan putranya yang
bungsu bernama Sri Kresna Wangbang Kepakisan dan dilantik menjadi
Adipati, abiseka Dalem Ketut Kresna Kepakisan, berkedudukan di
Samprangan pada tahun 1352 M. Kedatangan Dalem Ketut Kresna Kepakisan di
Bali didampingi oleh 11 para Arya, yaitu: Arya Kanuruhan, Arya
Wangbang, Arya Demung, Arya Kepakisan, Arya Tumenggung, Arya Kenceng,
Arya Dalancang, Arya Belog, Arya Munguri, Arya Pangalasan dan Arya
Kutawaringin (Anak Agung Ktut Agung, 1991: 12., S. Swarsi, dkk,
1998/1999: 27-30).
Dalem Ketut Kresna Kepakisan beristana di Samprangan, sedangkan Patih
Baginda di Nyuhaya, sehingga terkenal sebutan I Gusti Nyuhaya di
masyarakat. Adapun para menteri yang lainnya diberikan tempat kedudukan
masing-masing, Arya Kutawaringin di Klungkung, Arya Kenceng di Tabanan,
Arya Belog di Kaba-Kaba, Arya Dalancang di Kapal, Arya Belentong di
Pacung, Arya Sentong di Carang sari, Arya Kanuruhan di Tangkas, Arya
Kriyan Punta di Mambal, Arya Jrudeh di Tamukti, Kriyan Tumenggung di
Patemon, Arya Demung Wang Bang Kediri di Kretalangu, Arya Sura Wang Bang
Lasem di Sukahet, Arya Wang Bang Mataram tidak menetap di suatu tempat
dan boleh dimana saja, Arya Melel Cengkrong di Jembrana, Arya Pamacekan
di Bondalem, Arya Gajah Para dan adiknya yaitu Arya Getas bertempat di
Toyanyar. Begitulah asal mulanya, dan seluruh penempatan ini atas
perintah Patih Gajah Mada (I B Rai Putra, 1991: 10-11).
Arya Malel Cengkrong di tempatkan di Jembrana adalah arya dari Pejarakan
merupakan pasukan berkuda Majapahit. Setelah Arya Malel Cengkrong
wafat, digantikan oleh keturunannya yakni I Gusti Ngurah Gde Pecangakan,
I Gusti Ngurah Bakungan dan I Gusti Ngurah Pancoran. I Gusti Ngurah
Bakungan mendirikan istana di daerah Gilimanuk Cekik yang bernama Puri
Bakungan, sedangkan I Gusti Ngurah Pecangakan mendirikan istana yang
bernama Puri Pecangakan dan I Gusti Ngurah Pancoran menjabat Manca agung
di Pacangakan.
Awalnya kedua kerajaan ini hidup berdampingan dengan damai, namun
akhirnya mengalami persaingan karena disebabkan oleh seekor kuda. I
Gusti Ngurah Gde Pecangakan memiliki kuda putih yang bernama Jaran Rana.
I Gusti Ngurah Bakungan ingin sekali memiliki kuda putih tersebut.
Akhirnya terjadi peperangan antara Bakungan dengan Pecangakan yang
berawal dari upacara adat Dewa Yadnya di Puri Bakungan. I Gusti Ngurah
Gde Pecangakan diundang untuk menghadiri upacara, namun undangan ini
dianggap prasangka buruk dan beliau berpesan kepada I Gusti Ngurah
Pancoran dan segenap keluarga puri, “Apabila kudaku kembali ke istana
(puri) bermandikan darah tanpa aku datang, itu berarti aku telah tertipu
dan terbunuh oleh adik Bakungan. Para istri supaya melakukan bunuh diri
(dharma satya) dan segenap harta benda (raja brana) disembunyikan di
dalam tanah puri. Arya Pancoran harus menuntut balas dan menghancurkan
habis-habisan istana/puri dan isi Bakungan”.
Setelah pesan disampaikan, rombongan I Gusti Ngurah Pecangakan beragkat
ke Bakungan dan sampai disana diterima dengan baik. Keesokan harinya
diadakan penyembelihan ternak sapi, kerbau dan babi untuk perlengkapan
upacara. Kuda putih kesayangan I Gusti Ngurah Gde Pecangakan menjadi
liar dan lepas dari kandangnya. Kejadian ini dilaporkan dan
diperintahkan untuk segera mengejarnya namun tidak berhasil. Kuda putih
yang melarikan diri dari Bakungan tiba di Pecangakan sehingga
mengejutkan keluarga puri dan seluruh rakyatnya. Karena teringat dengan
pesan yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Gde Pecangakan, maka para
istri melakukan bunuh diri (satya) dan harta benda disimpad di dalam
sumur puri. I Gusti Ngurah Pasncoran dengan pasukannya berangkat ke
Bakungan untuk menuntut balas dan menghancurkan Puri Bakungan, namun
tidak menemukan mayat I Gusti Ngurah Gde Pecangakan. Akhirnya diputuskan
untuk kembali pulang ke Pecangakan, dan setelah tiba di Pecangakan I
Gusti Ngurah Pancoran kaget karena I Gusti Ngurah Gde Pecangakan masih
hidup, lalu diceritrakan hal yang mereka lakukan di Bakungan. Akhirnya I
Gusti Ngurah Bakungan murka dan menantang perang tanding dengan I Gusti
Ngurah Gde Pecangakan di sebuah pulau kecil di sebuah sungai yang
disebut pulau kembar. Dalam perang tanding itu keduanya sama-sama tewas.
Para arya, brahmana dan rakyat yang masih hidup menamakan daerah/negeri
Bakungan dan Pecangakan yang telah musnah disebabkan oleh kuda putih
bernama Jaran Rana dengan nama Jembrana (Buda, 1990: 24-26). Bahkan
Danghyang Nirartha dalam perjalanannya ke Bali dari Pulau Jawa
menyebutkan daerah Bali barat yang dikunjunginya dengan nama Jembrana
(Toetoer Lambangkawi, No. 1339/Va: 1-2).
Ada lagi ceritra yang beredar di masyarakat bahwa Jembrana berasal dari
Jimbar Wana yang diartikan sebagai berikut; Jimbar artinya besar, Wana
artinya hutan. Jimbaran Wana artinya hutan yang besar. Dari
cerita-cerita itulah kemudian kata-kata Jaranbana menjadi Jembrana.
Begitu pula kata-kata Jimbar Wana menjadi Jembrana. Meskipun cerita
dongeng ini telah lama tersebar di antara desa-desa yang ada dengan
versi yang berbeda-beda, namun kenyataannya cerita ini masih tetap hidup
di kalangan masyarakat Jembrana sampai saat ini (Jayus, 1993: 1-2).
a. Asal-Usul Nama Negara.
Kota Negara yang ada sekarang ini termasuk wilayah swapraja Jembrana
sejak masa pemerintahan Sunda Kecil, begitu pula pada masa pemerintahan
Bali dan Nusa Tenggara (Raka, 1955: 101). Nama Negara berdasarkan kisah
di masa lampau atau berdasarkan legenda yang berkembang di masyarakat
ada dua versi yakni: Negara berasal dari kata Naga Ru yang artinya Naga
Dua, menurut penuturan kakek A. Damanhuri bernama Harun yang juga
sebagai guru penari di puri Negara. Beliau wafat pada tahun 1952 dengan
usia 125 tahun menuturkan bahwa, beliau berkali-kali menyaksikan
bilamana terjadi air banjir besar di Sungai Ijo Gading terlihat dua buah
cahaya seperti lampu terapung mengikuti arus menuju muara. Konon cahaya
itu adalah dua ekor ular naga, menuju hutan Gunung Sembulungan (timur
Kota Muncar Banyuwangi). Kisah tersebut sangat memasyarakat dikalangan
umat Hindu dan Muslim Jembrana, sehingga kisah tersebut merasuk ke dalam
jiwa para seniman Jembrana, terbukti bila para seniman Jembrana melukis
atau mengukir pada alat-alat kesenian tidak luput dari lukisan atau
ukiran berupa dua ekor naga sebagai penghiasnya.
Negara juga berasal dari kata Negari yang dikaitkan dengan sebutan kota
yang dibangun pada tahun 1679 di atas kawasan Negara, yang kini disebut
kota lama. Orang-orang suku bugis dan Melayu yang datang ke Jembrana
memasuki kawasan Negara mulai tahun 1653-1669, secara umum menggunakan
bahasa melayu yang hingga kini disebut bahasa Loloan. Oleh karena itu
maka sebuah kota menurut orang-orang Melayu disebut Negari, sehingga
Puri Agung yang dibangun oleh kerajaan Jembrana, letaknya kira-kira 1 Km
sebelah utara kota selesai dibangun pada tahun 1803 diresmikan dengan
nama Puri Agung Negari. Semakin lama kota semakin ramai dan bertambah
maju, sehingga Puri Agung Negari berubah namanya menjadi Puri Agung
Negara yang kemudian menjadi Kota Negara (Damanhuri, 1993: 1-2). Ada
juga yang menyebutkan bahwa Negara berasal dari kata Sansekerta yang
artinya Kota (Parwata, 1994: 19).
Menurut Achmad Damanhuri, menyebutkan bahwa sejak diresmikannya kota
lama oleh penguasa I Gusti Ngurah Pancoran pada tahun 1679 merupakan
indikasi dan sekaligus merupakan batu pijakan bagi awalnya sejarah
lahirnya Kota Negara sebagai Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II
Jembrana. Sedangkan menurut Ida Pedanda Gede Sigaran dan I Ketut Serung
mengemukakan bahwa Kota Negara lahir pada Purnamaning Kasa, tanggal 27
Juni 1800. Lahirnya kota Negara identik dengan berdirinya istana raja,
di mana letak istana raja di sanalah letak pusat pemerintahan dan
sekaligus menjadi ibu kota kerajaan. Penentuan angka tahun tersebut
didasarkan pada pendirian Puri agung Negeri oleh Anak Agung Putu Seloko
yang terletak satu kilo meter sebelah utara bandar Pancoran, dan pada
saat itu juga raja Anak Agung Putu Seloko berpindah dari Puri Gede
Jembrana ke Puri Agung Negeri sebagai pusat pemerintahan Kerajaan
Jembrana.
Berdasarkan data arsip, identifikasi mengenai hari, tanggal, bulan dan
tahun kelahiran kota, dalam hal ini kelahiran Kota Negara telah
ditemukan dalam Staatsblad van Nederlandsch-indie No. 175 tahun 1895
mengenai nama-nama ibu kota (hoofdplaatsen) afdeeling-afdeeling Buleleng
dan Jembrana. Staatsblad-staatsblad sebelumnya sama sekali belum pernah
menyebutkan adanya perkataan hoofdplaat (ibu kota) terhadap Negara
secara resmi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sumber
resmi yang diundangkan dan diterbitkan oleh Pemerintah Dalam Negeri
atas nama Ratu, dengan perwakilannya Gubernur Jenderal di Hindia
Belanda, dapat disebut sebagai fakta lahirnya Ibu Kota Negara.
Dinyatakan mulai berlakunya sejak ditetapkan di Buitenzorg tanggal 15
Agustus 1895, hari Kamis Paing, wuku Prangbakat (Tim Penulis, 1997:
55-59).
Demikianlah dikisahkan asal-usul nama daerah yang terletak diujung barat
pulau Bali yang sampai kini masih tetap disebut Jembrana dengan Ibu
Kotanya Negara.
b. Masuknya Suku Pendatang di Jembrana.
Mengenai kapan masuknya orang-orang asing ke Bali, khususnya di Jembrana
belum dapat dipastikan karena sumber-sumber yang mendukung belum
ditemukan. Sumber lokal menyebutkan bahwa kedatangan orang asing yang
pertama di Jembrana adalah orang Bugis pada pertengahan abad 17. Mereka
datang dari Makasar sewaktu terjadi peperangan antara kerajaan di
Sulawesi Selatan. Pada saat itu juga datang pasukan Belanda (VOC) untuk
merebut daerah Makasar, dan berhasil merebutnya setelah diadakan
perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Abad ke-16 di Sulawesi Selatan telah
ada beberapa kerajaan yang berdiri sendiri seperti Kerajaan Gowa-tallo,
Wajo, Bone, Luwu dan Sopeng. Persaingan antar kerajaan terjadi terutama
kerajaan Gowa dengan kerajaan Bugis (Wajo, Luwu, Bone, dan Sopeng).
Peperangan antar kerajaan terjadi karena perebutan kekuasaan di
Sulawesi Selatan. Dalam peperangan Gowa selalu unggul dibandingkan
dengan Bone, sehingga Bone bersekutu dengan Wajo dan Sopeng. Persatuan
tiga kerajaan Bugis (Wajo, Bone dan Sopeng) disebut Tellumpoccoe (Buda,
1990: 43-44).
Gerakan peng-Islaman yang diserukan kerajaan Gowa ditolak oleh
persekutuan kerajaan Bugis, sehingga terjadi peperangan di Sulawesi
Selatan. Satu persatu kerajaan Bugis dapat ditaklukkan seperti Sopeng
dapat ditundukkan pada tahun 1609, Wajo ditundukkan tahun 1610 dan
Kerajaan Bone dapat ditaklukkan pada tahun 1611. Gerakan peng-Islaman di
Sulawesi selatan baru dianggap selesai setelah Kerajaan Bone menerima
Islam sebagai agama resmi kerajaan.
Sejak perjanjian Bongaya dilaksanakan di Sulawesi Selatan tahun 1667,
terdapat orang-orang Bugis yang bermigrasi ke Jawa. Pelarian orang-orang
Bugis ini membawa dendam kepada Belanda, begitu pula Belanda berusaha
menghancurkan orang-orang Bugis yang dianggap membahayakan kekuasaan
pemerintah Belanda. Orang-orang Bugis mengembara sambil memberikan
bantuan kepada para musuh-musuh kompeni (VOC).
Di Bali pengaruh kekuatan Belanda pada abad ke-17 dan 18 belum begitu
nampak sehingga pelarian orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan dengan
aman dapat berlabuh di pantai-pantai pulau Bali. Di Bali mula-mula
mereka mendarat di tiga tempat yakni di pantai Lingga di Buleleng,
Serangan di Badung dan Air Kuning di Jembrana.
Pendaratan orang-orang Bugis di pantai Lingga Buleleng terjadi karena
menyerahnya Raja Hasanudin kepada Belanda dan pada tahun 1667 terpaksa
Makasar diserahkan.Sejak itulah banyak orang-orang Bugis dan Mandar
yang melarikan diri ke selatan yang antara lain ke Bali di antaranya ada
yang bertempat tinggal di pantai Lingga Buleleng. Karena orang-orang
ini dianggap bajak laut oleh Belanda dan oleh penduduk Buleleng sehingga
Aji Mampa dan pengiringnya terpaksa meninggalkan pantai Lingga menuju
ketimur dan menetap di sebuah kampung Bugis (Ginarsa dalam Saidi, dkk,
2002: 73-77).
Masuknya orang-orang Bugis di Serangan- Badung, ditinjau dari sudut
ekonomi terjadi karena adanya hubungan dagang antara orang-orang Bugis
dari Sulawesi Selatan dengan orang-orang Bali yang bertempat tinggal
dalam wilayah kerajaan Badung sejak abad ke-17. Dari hubungan dagang
akhirnya meningkat kepada hubungan yang bersifat persahabatan di antara
orang-orang Bugis tersebut dengan pihak kerajaan Badung. Bukti-bukti
yang menunjukkan hubungan baik tersebut adalah sewaktu kerajaan Badung
memerlukan prajurit-prajurit andalan yang sangat dibutuhkan pada waktu
menggempur Mengwi. Penyerbuan terhadap Mengwi dilakukan oleh kerajaan
Badung dengan menggabungkan pasukannya sendiri ditambah dengan pasukan
Bugis serta Raden Sastroningrat dengan pengikut-pengikutnya. Dengan
pasukan gabungan ini akhirnya kemenangan dapat tercapai.
Bukti lain yang juga menunjukkan hubungan baik antara kerajaan dengan
orang-orang Bugis ketika daerah Jembrana sebagai pusat kekuatan
orang-orang Bugis di Bali menjadi vazal kerajaan Badung, maka
menempatkan seorang Kepala orang-orang Bugis di Jembrana yaitu Kapten
Patimi sebagai wakil . Jadi Kapten Patimi ini di samping diangkat
sebagai wakilnya juga bertindak sebagai syah bandar. Hubungan baik ini
sekarang dilanjutkan terus dan tidak jarang juga raja membantu keperluan
orang-orang Bugis tersebut, dan jika orang-orang Bugis ini berkunjung
ke Puri Pemecutan mereka menghadap tidak sebagai halnya rakyat menghadap
kepada raja, melainkan menghadap raja sebagai layaknya seorang sahabat
yang berkunjung kepada sahabatnya. Mesjid yang ada di Pulau Serangan
yang termasuk Mesjid pertama dan tertua di Badung dibangun dengan biaya
kerajaan, termasuk juga pembelian marmer yang dipasang pada Mesjid
tersebut adalah merupakan barang perdagangan import dari India yang
masuk lewat Singapura.
Peninggalan lain orang-orang Bugis adalah kompleks makam yang terdapat
di Pulau Serangan. Makam ini mempunyai persamaan dengan makam-makam yang
ada di Kepaon maupun makam-makam yang ada di Angan Tiga Petang. Makam
di Pulau Serangan ini ada yang menarik perhatian yaitu makam ini
mempunyai bentuk lain dari bentuk makam yang ada disekitarnya, di mana
makam ini merupakam perkembangan dari bentuk cungkup yang disebut
kubang (kubah) (Wirawan, dan Dian Arriegalung, dalam Shaleh Saidi ,
2002: 19-25).
Masuknya pengaruh orang-orang Bugis di Air Kuning Jembrana sudah terjadi
pada abad ke-16. Pada zaman itu terjadi peperangan antara
kerajan-kerajaan di Sulawesai Selatan, yang disambung dengan peperangan
melawan tentara Belanda hingga abad ke-19. Akibat dari peperangan ini
sehingga mereka pindah ke daerah-daerah pantai timur dan utara Sumatra,
pantai barat dan selatan Kalimantan (orang Bugis Pegatan), Banten (Jawa
Barat), Pasuruan (Jawa Timur), Badung Bali dan yang terakhir di Air
Kuning Jembrana. Pendaratan di Air Kuning dipimpin oleh Daeng Nachoda
sekitar tahun 1669 dan masuk kuala Perancak. Mereka berhasil mendarat
dengan mempergunakan perahu perang jenis “Lambo dan Pinisi” yang
berisikan senjata api, meriam-meriam serta senjata tombak, badik dan
keris. Rombongan ini menetap sementara disebuah tempat yang mereka
namakan Kampung Bali. Sebuah sumur air tawar yang jernih hingga kini
masih ada disebut oleh warga sekitar dengan nama Sumur Bajo yang
terletak ditepi kuala Perancak sebelah barat. Akhirnya mereka mengetahui
bahwa daerah yang mereka tempati bernama Jembrana. Mereka diberi izin
oleh penguasa daerah Jembrana (marga Arya Pancoran) untuk menetap di
Pancoran. Tempat pendatang dari Bugis ini terkenal dengan nama pelabuhan
Bandar Pancoran (pelabuhan lama di Loloan Barat) (Suwita, dalam
Depdikbud RI, 1997: 173).
Setelah pertengahan abad ke-18, disusul pula oleh orang-orang dari
Kalimantan Barat (Pontianak). Di Kalimantan Barat terdapat koloni atau
perkampungan orang-orang Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Di
bawah pimpinan Syarif Abdullah bin Yahya Al Qadry orang-orang Bugis
dapat merebut sebuah kapal Perancis dan sebuah kapal Inggris di Pantai
Kalimantan Timur tahun 1770 dan 1771. Karena syarif Abdulah tidak setuju
dengan perjanjian yang dibuat oleh Belanda tahun 1779 dengan kerajaan
Pontianak, maka mereka bersama anak buahnya meninggalkan negerinya
menuju ke Bali dan mendarat di Air Kuning Jembrana. Di Air Kuning mereka
bertemu dengan orang Bugis yang dipimpin oleh Haji Shihabuddin yang
telah lebih dahulu menetap di sana. Atas bantuan pemuka orang Bugis di
Air Kuning Syarif Abdullah dan anak buahnya diantar menghadap kepada
Raja Jembrana dan akhirnya mereka diijinkan mendiami daerah di sebelah
kiri dan kanan Sungai ijogading. Tempat pemukiman mereka ini kemudian
diberi nama Loloan yang terletak di sebelah utara Bandar Pancoran (Buda,
1990: 49-51).
Kedudukan orang-orang asing yang beragama Islam bertambah kuat dengan
kedatangan Encik Yaqub, orang Melayu dari Trengganu mewakapkan sebuah Al
Qur’an dan sebidang tanah sawah di Merta Sari untuk pembiayaan dan
pemeliharaan Mesjid Loloan. Pewakapan ini terjadi pada masa Pak Mahbubah
menjadi penghulu, Pak Mustika sebagai Pembekel, disaksikan oleh Syarif
Abdullah bin Yahya Al Qodry dan khatif adalah Abaa Abdullah Hamnaa.
Tanah wakaf di Mertasari adalah seluas 0,45 ha, selain itu terdapat juga
di Desa sembati seluas 0,90 ha, di Subak Tugtug seluas 1,05 ha, di
Subak Cupel 1,25 ha, dan 1,50 ha terletak di DesaSang Jangkrik (Buda,
1990: 51-52).
Suku pendatang lainnya adalah orang-orang Jawa, Madura, Sasak Cina dan
Eropa. Latar belakang mereka beremigrasi ke Bali khususnya ke Jembrana
belum ada sumber yang membicarakan hal ini. Namun mereka ini pernah
menetap atau setidak-tidaknya pernah menyinggahi Jembrana di masa lampau
yang kini anak-anak cucunya di antara mereka masih ada di Jembrana.
Hubungan Jawa dan Madura dengan Bali di satu pihak, dan hubungan Bali
dan Lombok di pihak lain sudah terjadi di masa lampau. Hal ini tidak
mustahil akan dapat mendorong persebaran orang-orang Jawa, Madura, Sasak
maupun orang asing lainnya yang berada di Lombok maupun yang ada di
Pulau Jawa. Persebaran terjadi setelah perhubungan laut semakin lancar
karena perdagangan di Jembrana semakin terbuka dan ramai.
Penyebrangan orang Jawa, Madura dan Sasak ke Bali nampak pula dilakukan
melalui saluran ekspedisi militer atau peperangan. Dalam ekspedisi
Militer Belanda ke Bali tahun 1846 diikutsertakan pasukan dari Madura
sebanyak 500 orang, dalam pertempuran di Jagaraga tahun 1849 juga
didatangkan tenaga kasar dari Jawa Timur sebanyak 2000 orang yang
terdiri dari orang-orang Jawa dan Madura. Setelah memperoleh kemenangan
di Jagaraga, di bawah pimpinan Jendral Michiels Belanda melanjutkan
ekspedisinya menuju ke Karangasem. Di Karangasem Belanda memperoleh
bantuan dari pasukan Lombok sebanyak 4000 orang. Fakta-fakta tersebut
dapat menggambarkan bahwa baik orang-orang Jawa, Madura maupun orang
Lombok (Sasak) kerap meninggalkan pulaunya untuk melawat ke daerah lain
seperti Bali dalam rangka peperangan (Buda, 1990: 56-59).
Orang-orang Eropa datang karena tertarik karena kemajuan dan kemakmuran
daerah Jembrana. Mula-mula mereka datang sebagai pelancong dari
banyuwangi. Pada tahun 1860 De Mey Van Gerwen datang di Jembrana untuk
memohon tanah Indra Loka kepada I Gusti Made Pasekan. Setelah dikabulkan
pada tanggal 17 januari 1861 mereka menetap di tanah perkebunan Indra
Loka untuk memulai usaha pertanian. Pada tahun 1863 De Mey Van Gerwen
menetapkan tanah Indra Loka bernama Candi Kuning.
Pada abad ke-19 hubungan perniagaan bertambah ramai, terkenal dengan
pengiriman ternak sapi dan kerbau ke Jawa. Perniagaan selain dilakukan
oleh orang-orang Bugis, juga nampak dilakukan oleh orang-orang Cina dan
Madura yang keluar masuk dari dan ke pelabuhan Loloan. Menurut laporan
Raden Sosrowidjojo dalam perjalannya ke Bali khususnya di Jembrana
menyebutkan bahwa pada tahun 1871 sudah terdapat orang-orang Cina yang
menetap di Loloan. Sebagai bukti orang Cina pernah menetap di Jembrana
diperkuat dengan adanya peninggalan batu nisan tertulis pada kuburan
orang Cina di Jembrana memakai angka tahun 1883. Jadi informasi ini
memperkuat bahwa orang-orang Cina sudah menetap di Jembrana pada abad
ke-19 (Buda, 1990: 61-62).
c. Datangnya Ulama-Ulama Besar di Jembrana.
Pada tahun 1669 telah datang empat ulama besar yang menyampaikan ajaran
Islam. Mulanya mereka memberikan dakwah di Air Kuning selama dua tahun.
Ulama-ulama tersebut adalah; Pertama, Shofi Sirojuddin, datang dari
Betawi berkebangsaan Melayu asalnya dari Serawak Malaysia Timur. Mereka
akhirnya bermukim di Loloan Timur sampai akhir hayatnya. Orang Bugis
menyebutkan Oding, sedang orang-orang memberi gelar Lebai, dan dikenal
dengan nama Buyut Lebai. Kedua, Syeh Ahmad Fauzir, beliau berasal dari
Jawa Timur berkebangsaan Aden Yaman. Beliau melakukan dakwah ajaran
Islam di Loloan. Beliau mempunyai putra yang bernama Syeh dato Ibrahim
yang lahir di Loloan Timur dan menjadi ulama besar di Banyuwangi, serta
dikenal sebagai orang keramat. Ketiga, H. Syihabuddin, beliau datang
dari Buleleng dan tergolong suku Bugis. Beliau memberikan dakwah Islam
dan menetap di desa Air Kuning. Dengan dakwah-dakwah yang disampaikan
beliau, maka memperkuat iman dan ajaran Islam di Jembrana. Keempat, Haji
Yasin, adalah salah seorang ulama besar yang datang dari Buleleng.
Beliau juga ikut memperkuat ajaran Islam di Jembrana. Beliau adalah
keturunan orang Bugis dan sering berdakwah di Loloan Barat (Damanhuri,
1993: 5-6).
C. PENGABDIAN SYARIF ABDULLAH BIN YAHYA AL QODRI (SYARIF TUA) DI JEMBRANA 1799 – 1858
a. Asal-Usul Keluarga.
Menurut I Wayan Reken, bahwa Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri
berasal dari Pontianak, ayahnya adalah seorang Ulama Arab yang
termasyur. ia nikah dengan ibunda Raja di Matan. Kemudian ia diangkat
menjadi Kadi Agung. Karena sesuatu hal maka ia pindah ke Mampawah. Pada
tahun 1770, ia mangkat dan meninggalkan putra Syarif Abdurrahman dan
Syarif Abdullah dari perkawinannya dengan Ibunda Raja Matan.
Syarif Abdurrahman menikah dengan putri Raja Mampawah, sedangkan Syarif
Abdulah bin Yahya Al Qodri menikah dengan putri Sultan Banjarmasin yang
bernama Fatimah. Pada tahun 1771 Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri di
pantai timur Kalimantan dekat Pasir mereka merampas sebuah kapal milik
Prancis dan sebuah kapal Inggris. Kejadian ini membuat situasi menjadi
panas sehingga mertuanya yaitu Sultan Banjarmasin menyuruhnya pergi.
Pada tahun 1772 didirikan Kerajaan Pontianak oleh Syarif Abdurrahman dan
Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri bersama kawan-kawannya serta dibantu
oleh orang-orang Bugis yang berkampung di Pontianak kurang lebih
jumlahnya 400 orang. Orang-orang Bugis ini berasal dari Sulawesi. Negara
yang baru dibentuk maju dengan pesat dan banyak dikunjungi oleh
orang-orang untuk kegiatan perdagangan. Oleh karena itu kerajaan
Pontianak menjadi hal yang menarik bagi oang-orang asing terutama bagi
Kompeni Belanda (dan Reken, 1979: 10-11). Kerajaan Pontianak ini
dipimpin oleh Abdul Rahman bin Husin Al Qodri sebagai Sultannya,
sedangkan Abdullah bin Yahya Al Qodri adalah sebagai wakilnya, dan
dibantu oleh seorang bangsa Melayu asal Kedah sebagai Panglima Perang
Kesultanan, yang bernama Dato Ahmad Muntahal.
Baru saja pemerintahan Kerajaan Pontianak berlangsung 8 tahun, timbullah
rasa iri atau ingin menguasai dari pemerintah Belanda (VOC) terhadap
kemajuan yang dicapai Pontianak terutama di bidang perdagangan. Sultan
Pontianak Abdurrahman bin Husin Al Qodri yang baru saja menduduki
singasana kesultanan, mendadak mendapat tekanan atau teror dari
pemerintahan Kompeni Belanda. Sultan dipaksa untuk mau bekerjasama
dengan Belanda terutama di bidang perdagangan di negeri Pontianak.
Karena Belanda memaksa dengan kekerasan, akhirnya dengan sangat terpaksa
Sultan Pontianak menandatangani kerjasama di bidang perdagangan dengan
Belanda.
Sejak ikut campurnya Belanda di dalam Kerajaan Pontianak mengakibatkan
terjadinya perpecahan di dalam kerajaan. Pada tanggal 5 Juli 1779
Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Pontianak Syarif Abdurraman
(Jabar, 2008: 10-13). Hal ini dipandang perlu dilakukan oleh Belanda
untuk menghindarkan terjadinya peperangan-peperangan, Kompeni mengadakan
pendekatan dengan kontrak, di mana Sultan Pontianak Syarif Abdurrahman
mengakui Kompeni sebagai tuannya. Tunduknya atau pengakuan Sultan
Pontianak kepada Kompeni ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kompeni.
Hal ini terbukti pada waktu Kompeni menghadapi Mampawah, Sultan
Pontianak membantu Kompeni untuk membinasakan kerajaan Mampawah dan
Sukadana yang berlangsung pada tahun 1786-1787. Dengan demikian segala
perniagaan beralih ke Pontianak (Reken, dalam Shaleh Saidi, 2002: 52-53
dan Reken, tanpa tahun: 10-11).
Menurut I Wayan Reken, dalam tulisannya Sejarah Perkembangan Islam di
Bali Khususnya di Jembrana, menyebutkan bahwa Sultan Pontianak Syarif
Abdurrahman Al Qodri katanya bersaudara dengan Syarif Abdullah bin Yahya
Al Qodri. Hal ini menurut Bapak H. S. Yasin Al Qadri tidak benar bahwa
Syrif Abdullah bin Yahya Al Qodri adalah adiknya/saudara Sultan
Pontianak Syarif Abdurrahman Al Qodri. Syarif Abdullah adalah memang
benar ada hubungan darah dengan Syarif Abdurrahman, namun jauh di bawah
dan bukan bersaudara. Setelah menetap di Jembrana Syarif Abdullah bin
Yahya Al Qodri mempunyai seorang istri yang bernama Sipunce yang berasal
dari Jembrana. Dari perkawinannya ini beliau mempunyai lima anak yakni:
Usman (laki-laki), Muhammad (laki-laki), Husin (laki-laki), Ibu Ami
Agil (perempuan), Sarifa Encu (perempuan).
Pernyataan H. S. Yasin Al Qadri diperkuat oleh pernyataan H. Husein
Jabar bahwa Syarif Abdurrahman (Sultan Pontianak) tidak mungkin
bersaudara dengan Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri. H. Husein Jabar
menjelaskan Sultan Pontianak Kalimantan Barat yang berkuasa sejak
1771-1808 M, namanya Sayid Abdul Rahman suku Arab Hadrmaut bin Husin bin
Ahmad Al Qodri. Ayahnya yaitu Husin bin Ahmad Al Qodri pada tahun 1735 M
datang dari Hadramaut di Matan. Selanjutnya Sayid Husin Al Qodri
menikah dengan Putri keluarga Matan, yang hanya disebut Ibunda di Matan.
Dari pernikahan tersebut lahirlah putranya yang bernama Abdul Rahman.
Setelah beberapa lama tinggal di Matan, maka Sayid Husin Al Qodri
beserta keluarganya pindah ke Mampawa. Di Mampawa Sayid Husin diangkat
sebagai pejabat penting yaitu menjadi Sekretaris Negeri, sampai ia
menutup usianya di sana. Sedangkan nama Syarif Abdullah bin Yahya Al
Qodri menurut H. Husin Jabar, secara otentik telah tersurat di dalam
Prasasti Loloan. Dari sinilah diketahui identitasnya masing-masing.
Abulrahman (Sultan Pontianak) itu bin Husin Al Qodri. Sedangkan Abdullah
itu adalah bin Yahya Al Qodri. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan
silsilah keluarga Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri sebagai berikut:
Habib Husein bin Ahmad Al Qodri
(Tuan Besar Mampua)
Syarif
Ahmad Syarif
Ali Syarif Abubakar Syarif Muhammad Syarif
Alwi Syarif Abdul Rahman
(Sultan Pontianak)
Syarif Yusuf Al Qodri
Sayid Muhammad Sayid Kasim Sayid Yahya
Syarif Abdul Razak Syarif Muham-
Mad Saleh Syarif Abdul Latif Syarif Mohha-
Mad Tohir Syarif Sulaiman Syarif Abdullah
(Srarif Tua)
Sumber: Koleksi pribadi H. S. Yasin Al Qodri di Jembrana.
Dilihat dari silsilah Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri di atas, maka
beliau adalah termasuk dari kalangan keluarga yang terpandang atau
seorang tokoh yang mempunyai karisma secara turun temurun. Seperti yang
telah dikemukakan di depan bahwa munculnya seorang pemimpin dalam hal
ini Syarif Abdullah bin Yahya Al Qadri sebagai seorang tokoh yang baik.
Secara garis keturunan memang Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri adalah
keturunan yang memiliki bakat-bakat menjadi seorang pemimpin. Lingkungan
keluarga pada masa itu yang penuh dengan gejolak atau menghadapi bangsa
penjajah Belanda maka beliau sudah biasa hidup dilingkungan kekerasan.
Hal ini membentuk karakter atau pribadi Syarif Abdullah yang tegar,
penuh semangat dan tidak mau ditundukkan, dijajah oleh bangsa Belanda.
Oleh karena itu beliau tidak puas pada waktu Sultan Pontianak Syarif
Abdrrahman mau menyerahkan kedaulatan negerinya kepada Kompeni Belanda
pada tahun 1799. Kesepakatan bekerjasama ini yang ditandai dengan
penandatanganan traktat dengan Belanda, membuat Syarif Abdullah murka
serta memutuskan membrontak kepada Belanda dan melarikan diri untuk
mencari daerah baru yang belum banyak dipengaruhi oleh Belanda. Karena
beliau adalah tokoh yang sangat dihormati sehingga beberapa anak buahnya
yang setia ikut bersamanya.
b. Tiba di Kampung Loloan.
Syarif Abdullah bin Yahya Al Qadry menggunakan empat perahu perang
dengan muatan persenjataan lengkap seperti meriam, badik, tombak dan
keris. Mereka berhasil mendarat di air Kuning (Jembrana) dan bertemu
dengan orang Bugis yang telah lama menetap di sana yang dipimpin oleh
Haji Shihabuddin. Haji Shihabuddin memberikan ijin kepada mereka untuk
masuk ke Kuala Perancak dan berlabuh di pelabuhan darurat Air Kuning.
Atas bantuan pemuka orang Bugis ini Syarif Abdullah bersama rombongannya
diantar menghadap kepada Raja Jembrana Anak Agung Putu Seloka (Raja
ketiga yang memerintah dari tahun 1795-1842). Sejak tahun 1799 Raja
Jembrana mengijinkan Syarif Abdullah beserta rombongannya untuk tetap
tinggal dan bermukim di sebelah kiri dan kanan Sungai Ijogading seluas
80 hektar (sekarang Loloan Barat dan Loloan Timur). Oleh raja mereka
ditugaskan menjadi Laskar Keamanan Rakyat dari negeri Jembrana yang
menjaga keamanan kerajaan Jembrana beserta rakyatnya (Sumerta, dkk,
2000: 9-10).
Di dalam perkembanganya desa Loloan terbagi menjadi dua bagian yaitu,
Loloan Timur dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan
tempat penduduk yang tertua di Loloan. Loloan Timur tidak membagi
desanya atas kampung-kampung hanya ada bagian Selatan, Tengah dan Utara.
Akan tetapi ada juga kampung yang diberi nama Kampung Sabo (karena
banyak pohon sawo), Kampung Merta Sari yang mayoritas penduduknya
beragama Hindu, karena letaknya di desa Merta sari, dan sebuah
perkampungan yang berisi suku Madura dan Jawa yang disebut Kampung Baru
terletak di batas Utara Desa loloan Timur. Sedangkan Loloan Barat,
merupakan gabungan dari beberapa kampung yaitu Kampung Terusan terdapat
di paling ujung Selatan desa dan kampung Loloan (dulu) di bagian Barat
Sungai Ijo Gading dan kampung yang lainnya (Panitia Pelaksana KKL, 1996:
12-16).
Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Negara, Jembrana merupakan salah satu
potret desa yang mampu menjaga kerukunan beragama di tengah-tengah
penduduk yang majemuk. Keberadaan Loloan Timur yang lokasinya berada di
tengah-tengah Kota Negara, dengan ketinggian 300 meter dari permukaan
laut, memiliki luas wilayah 4.340 ha. Jumlah penduduknya tahun 2008
adalah 6.055 orang dengan perincian laki-laki 2.965 orang dan 3.090
orang perempuan (Laporan Bulanan Desa/Kelurahan tahun 2008). Di sini
terlihat keberhasilan diterapkan kerukunan antar umat beragama dari
generasi ke generasi hingga sekarang. Kondisi yang kondusif tersebut
sangat didukung oleh pengertian warga Loloan timur dalam hidup
bermasyarakat. Walaupun mereka berbeda keyakinan, semangat untuk tetap
bersatu dan membangun kerukunan bermasyarakat tetap tinggi. Kerukunan
seperti itu bukan saja terjadi pada umat Hindu dan Islam, tetapi juga
dengan umat Protestan, Katolik dan Budha. Kerukunan yang terjalin antar
umat beragama dapat terlihat dari adanya saling bantu dalam berbagai
kegiatan.
Rasa persaudaraan juga terlihat pada saat menjelang hadirnya hari-hari
besar agama. Di samping saling bersilahturahmi di antara umat yang
berbeda agama, juga terlihat keterlibatan dalam melaksanakan aktivitas
untuk upacara keagamaan. Sebagai suatu contoh, pada saat hari raya Nyepi
bagi umat Hindu pembuatan ogoh-ogoh bukan saja dilakukan oleh warga
umat Hindu, pemuda dari umat Islam pun membaur menjadi satu larut dalam
kerja hingga sampai saat mengusung ogoh-ogoh di hari Pengrupukan, petang
hari menjelang Nyepi. Pembauran keragaman dalam bingkai kesatuan
wilayah inilah yang menjadi modal dalam membangun sehingga daerah ini
menjadi maju. Keterikatan historis merupakan perekat kerukunan umat
beragama di Kelurahan Loloan. Mereka menyadari ikatan-ikatan historis
yang terjadi sejak jaman kerajaan perlu dilestarikan demi terwujudnya
keharmonisan antar umat beragama (Kantor Informasi Komunikasi dan
Pelayanan Umum Kab. Jembrana, 2002; 10-20).
c. Mengabdikan Hidupnya di Jembrana.
Setelah Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri berada di Jembrana dengan
bantuan Syah Bandar beliau diantar ke daerah yang sedang di bangun
bernama Negara, maka terkenanglah beliau akan pembangunan kota Pontianak
yang dirintisnya dulu. Besarlah hasrat beliau untuk menemui raja di
Puri Jembrana untuk menyampaikan rasa hormat beliau dan mengulurkan
tangan persahabatan dalam perdamaian. Mengingat Blambangan telah
dikuasai oleh Kompeni Belanda, uluran tangan persahabatan diterima
hangat oleh Raja Jembrana Anak Agung Putu Seloka pendiri kota Negara.
Salah satu syarat dari undang-undang kerajaan menetapkan bahwa semua
meriam-meriam, perahu-perahu eskadron Sarif Abdullah bin Yahya Al Qodri
harus dijual kepada kerajaan sebagaimana telah berlaku pada
perahu-perahu Bugis/Makasar terdahulu. Syarat tersebut ditolak secara
halus oleh Syarif Abdullah, serta berkesanggupan kehadapan raja untuk
membela kerajaan Jembrana melawan musuh ataupun Kompeni Belanda.
Beliaupun sanggup menurunkan meriam-meriamnya ke daratan, di manapun
beliau diberi ijin bermukim tetap dalam memajukan pembangunan dan
perniagaan kerajaan. Setelah raja berunding dengan segenap pegawai
bawahannya maka diputuskan perkenan mendiami kanan kiri tebing Sungai
Loloan seluas kira-kira 80 ha, sebelah utara Bandar Pancoran.
Meriam-meriam kemudian diturunkan, syarif Abdullah beserta anak buahnya
segera membangun perkampungan darurat untuk seluruh rombongan di sebelah
Timur Sungai Ijo Gading yang sekarang dikenal dengan Loloan Timur.
Atas perkenan Raja Jembrana syarif Abdullah bersama-sama anak buahnya
membangun sebuah benteng Islam diberi nama Benteng Fathimah (sesuai
dengan nama istri Syarif Abdullah, yakni putri Sultan banjarmasin).
Perahu-perahu perangnya dirubah menjadi perahu-perahu perniagaan yang
kemudian menjelajahi lautan sampai ke Singapura, Dataran tanah Melayu.
Lambat laun Bandar Loloan makin ramai berkat persatuan umat muslimin.
Pada tahun 1803 selesailah pembangunan kota Negara. Loloan Timur dan
Loloan Barat adalah desa administratif konsesi umat Islam di Kerajaan
Jembrana dan empat desa yakni Merta Sari, Lelateng, Banjar Tengah, dan
Baler Bale Agung adalah desa administratif berbentuk Desa Adat Bali
Hindu (Reken, tanpa tahun: 11-12., dan Damanhuri, 1993: 13-14).
Raja Anak Agung Putu Seloka mempunyai dua orang putra yaitu yang sulung
bernama Anak Agung Putu Ngurah menempati Puri Agung di Negara, putranya
yang ke dua bernama Anak Agung Putu Raka menempati Puri gde Jembrana dan
di Puri Anom bertempat Anak Agung Made Rai. Tahun 1828 terjadi
peperangan yang kedua kalinya antara Jembrana dengan Raja Buleleng Anak
agung Gde Karangasem yang tertarik dengan kemakmuran kerajaan Jembrana.
Raja Anak Agung Putu Seloka bersama adiknya Anak Agung Ngurah Made
Bengkol dan beberapa pengiringnya mengungsi dengan perahu Bugis ke
Banyuwangi (sekarang bernama Kampung Bali). Setelah raja selamat sampai
di Banyuwangi anak Agung Made Bengkol kembali ke Jembrana. Dalam
peperangan pasukan Jembrana dipimpin oleh I Gusti Ngurah Gde dari Jero
Pancoran yang didukung oleh pasukan Islam. Panglima perang Buleleng Anak
Agung Gde Karang beserta prajuritnya gugur dalam pertempuran, akhirnya
mundur kembali ke Buleleng. Kemudian adik panglima perang Buleleng yang
bernama Anak Agung Made Karang menyerang dari arah laut, sedangkan dari
arah pegunungan pasukan Buleleng menyerbu Puri Jembrana dengan siasat
menjepit dari arah muka dan belakang. Karena begitu kuatnya musuh
akhirnya dalam perang tanding di Bajo/Awen panglima I Gusti Ngurah Gde
bersama Anak Agung Made Bengkol gugur, dan akhirnya Puri Gde Jembrana
dapat direbut. Namun Puri Agung Negara tidak berani didekati karena
banyak prajurit yang tertembak mati. Anak Agung Gde Karang kembali
memerintahkan anak buahnya mundur ke Buleleng.
Sampai tahun 1832, selama empat tahun Jembrana mengalami kekosongan
pemerintahan akibat peperangan dengan Buleleng, maka Syarif Abdullah bin
Yahya Al Qodri (karena sudah tua maka disebut Syarif Tua oleh penduduk
setempat) dan Panglima Tahal memperkuat posisi pertahanan Islam di
sekitar Benteng Fathimah, berpedoman pada prinsip agama yang sedang
dikembangkan melalui perwakilan dan berdagang, lebih bersifat asimilatif
dari pada revolusioner dan bukan sekali-kali untuk menaklukkan. Jika
pemuka Islam Syarif Abdullah beserta Panglima Tahal menghendaki dan
menyalahgunakan kesempatan sewaktu kerajaan Jembrana dalam keadaan
pemerintahan kosong selama empat tahun, maka pastilah pengaruh Islam dan
syarif abdullah bisa menguasai Jembrana. Akan tetapi Syarif Abdullah
adalah orang yang sangat bijaksana dan lurus hatinya, terutama setia
memegang teguh janji persahabatan dengan kerajaan Jembrana beserta
rakyatnya. Bahkan umat muslim selalu membantu rakyat yang sengsara
karena peperangan dan membinasakan musuh-musuh keraan Jembrana.
Tahun 1835 Raja Buleleng menginginkan perdamaian dengan Raja Jembrana
yang masih di banyuwang. Raja Jembrana Anak Agung Putu Seloka menerima
perdamaian ini dan kembali memerintah menempati Puri Agung Negara. Saat
itu semakin eratlah persatuan rakyat Muslim dengan rakyat Hindu. Karena
Raja Anak Agung Putu Seloka sudah tua maka pada tahun 1842 digantikan
oleh putranya yang sulung Anak Agung Putu Ngurah menjadi Raja Jembrana
bertempat di Puri Agung Negara dan putra keduanya Anak Agung Putu Raka
menjadi wakil raja bertempat di Puri Gde Jembrana. Sedangkan
kemenakannya Anak Agung Made Rai diangkat menjadi kepala perang kerajaan
bertempat tinggal di Puri Anom Jembrana (Reken, dalam Shaleh Saidi,
2002: 55-57).
Setelah menjadi Regentschap di bawah Residensi Banyuwangi, Kerajaan
Jembrana dikendalikan oleh tiga bersaudara. Hubungan perniagaan
Banyuwang-Jembrana makin ramai. Pada saat itu datanglah Alim Ulama dari
Jawa untuk meninjau perkembangan Agama Islam di Jembrana. Dengan penuh
kebijaksanaan Syarif Tua dan Sekh Fausie seorang Ulama dari Banyuwangi
memajukan perkembangan Islam. Mereka adalah tabib-tabib kenamaan yang
tak jemu-jemunya masuk ke daerah pedesaan, mendatangi orang yang sedang
sakit dan membutuhkan pertolongan. Beliau mengajarkan hikmah falsafah
Islam tanpa pilih kasih. Pengobatan yang beliau berikan cuma-cuma tanpa
suatu imbalan jasa, maka bersimpatilah rakyat jelata terhadapnya. Maka
makin percayalah rakyat akan kebenaran Agama Islam terutama di
pedesaan-pedesaan pantai Ketapang-Kombing (asal kata orang “mebading”)
artinya kaum beragama Hindu Bali beralih ke agama Islam.
Raja Anak Agung Putu Ngurah menaruh curiga kepada kegiatan Syarif Tua,
sehingga dengan cara halus melarang orang-orang Bali Hindu beralih agama
lain dengan perantara Ida Pedanda Agung , berdasarkan Hukum Adat
Istiadat yang berlaku. Syarif Tua sadar betapa tabyat Tuanku Raja, jauh
berbeda dengan ayahnya waktu berkuasa. Sering terjadi penindasan,
penganiayaan, kerja rodi, bea syahbandar terlalu besar dan terjadi
persaingan dalam kalangan kerajaan. Dengan segala kerendahan hati Syarif
Tua menemui raja Anak Agung Putu Ngurah untuk menyadarkan betapa
berbahayanya hawa nafsu dan kekuasaan itu. Namun raja tidak
memperhatikan nasehat yang disampaikan.
Seorang Punggawa bernama I Gusti Ngurah Made Pasekan yang sejak lama
menaruh kecewa terhadap raja, bersahabat dengan Syarif Tua dan seluruh
umat Muslimin. Diam-diam dia melayangkan surat gugatan kepada Komisarisw
Hindia Belanda tanggal 13 Oktober 1855 No. 85 di Residensi Banyuwangi.
Isi surat tersebut adalah rakyat Jembrana merasa sangat keberatan atas
ulah Raja Jembrana I Gusti Agung Putu Ngurah. Surat ini dilanjutkan oleh
Residen Banyuwangi ke hadapan Gubernur Jenderal di Betawi Bersamaan
dengan ini terjadi perpecahan di Jembrana, pihak pertama Punggawa
Jembrana I Gusti Ngurah Made Pasekan bersatu dengan Syarif Tua beserta
umat Islamnya dan prajurit-prajurit Pan Kelab beserta rakyat yang
berpihak kepadanya. Pihak kedua, Raja Jembrana, Ida Anak Agung Putu Raka
dikawal oleh bala tentara I Gusti Agung Made Rai dan seluruh Ksatria
yang berpihak. Jika dilihat dari kekuatan, pihak kerajaan jauh lebih
kuat. Syarif Tua mengumpulkan seluruh umat Muslim dari pedesaan-pedesaan
ke benteng Fathimah, Loloan Timur, begitu juga di sekitar Puri Negara
dan Jembrana telah penuh sesak dengan pengawalan. Peperangan tidak bisa
dihindari, dimana I Gusti Agung Made Rai mencabut keris “Tastas” pusaka
kerajaan dan I Gusti Made Pasekan mencabut keris pusaka Buleleng “Ki
tunjung Tutus”. Di lapangan Puri Jembrana dan Puri Negara penuh sesak
oleh prajurit pembela kerajaan. Tiba-tiba berdetumlah meriam-meriam
Syarif Tua dari Benteng Fathimah di Loloan Timur. Begitu juga
meriam-meriam Pan Kelabdari dekat arah Desa Pemedilan. Pasukan syarif
Tua juga dibantu oleh Panglima Datuk Tahal. Pertempuran sangat sengit,
di Benteng Fathimah Syarif Tua mengibarkan bendera Pusaka berwarna Hijau
bertuliskan kalimat Syahadat dan Panji-panji berwarna hitam bergambar
harimau berhuruf arab hadiah Sultan kedah dahulu yang berisikan ayat
Suci Al-Qur’an. Karena gempuran-gempuran dari Benteng Fatimah sehingga
Puri jatuh.
Pada malam hari Syarif Tua melakukan siasat kurungan terhadap Puri
Negara dengan laskar pilihan. Masing-masing membawa meriam tiruan dari
batang-batang pepaya yang dicat warna hitam untuk menakut-nakuti
prajurit kerajaan, seraya meminta suaka perundingan dengan tuanku Raja
Anak Agung Putu Ngurah. Syarif Tua selaku utusan umat Islam di Jembrana
di kawal oleh panglima Datuk Tahal. Syarif Tua membuka pembicaraan:
“Maaf Paduka Tuanku Yang Mulia, kami selaku utusan umat Islam dan
rakyat, memohon membuka musyawarah perihal kekuasaan yang mulia yang
diambang pintu keruntuhan. Sesungguhnya kami terlarang membunuh
orang-orang yang menyerah kalah. Demikianlah ajaran agama kami. Kami
mengangkat senjata bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk
menyebarkan agama sambil berniaga dan menolak sekeras-kerasnya
perbuatan-perbuatan dholim yang menghambat agama kami. Demi nama Allah
kami menasehatkan berangkatlah hesok pagi-pagi sebelum fajar dengan
segenap keluarga menyelamatkan diri untuk meminta perlindungan Hukum
kepada Gubernur Hindia Belanda. Tuanku Raja terdiam bingung menghayati
pembicaraan Syarif Tua sambil menimbang-nimbang, dan diputuskan Raja
beserta keluarganya meninggalkan Puri Negara menuju Buleleng. Raja juga
memerintahkan kepada Hulubalang-hulubalang supaya peperangan dihentikan,
karena kekuasaan kerajaan telah diserahkan secara damai kepada Syarif
Tua dan punggawa I Gusti Ngurah Made Pasekan. Keesokan harinya Raja
beserta keluarganya dan Anak Agung Made Rai menuju Buleleng.
Di Jembrana Raja I Gusti Agung Putu Ngurah dengan kemauannya sendiri
melepaskan hak kerajaan kepada Gouvernement Hindia Belanda, kemudian
menjadi Landschap Gouvernement di bawah seorang Regent, bertitel Raja I
Gusti Ngurah Pasekan. Tahun 1857 Anak agung Putu Ngurah dan keluarganya
ke Purwakarta (Jawa Barat). Semasa I Gusti Made Pasekan berkuasa, masa
itu adalah masa keemasan perkembangan Islam dan perniagaan di sekitar
Bandar Loloan. Keramaian berada di pusat pasar Loloan Barat berdekatan
dengan pelabuhan yang perahu-perahu tersebut melalui Kuala Perancak,
Tanjung Tangis mengangkut jemaah haji kemudian naik kapal dari pelabuhan
Surabaya.
Perkembangan pedesaan muslim meluas hingga ke Tegal Badeng, Rening dan
Pabuahan, dan orang-orang muslim di Air Kuning membuka hutan di Air
Sumbul. Dibuat pula sebuah jalan yang langsung menghubungkan
Jembrana-Loloan Timur atas perintah Tuan Komisaris. Benteng Fathimah
yang megah itu terpaksa dibongkar karena terkena jalur jalan. Selain itu
tanah benteng juga dipergunakan untuk perumahan. Pada tahun 1858 Syarif
Abdullah bin Yahya Al Qodri (Syarif Tua) wafat ke rehmatullah, di
kuburkan di peristirahatan terakhir, areal kuburan Loloan Timur/Barat
(Reken, dalam shaleh saidi, 2002: 60-68).
Demikianlah pengabdian yang dipersembahkan oleh Syarif Abdullah bin
Yahya Al Qodri (Syarif Tua) dari baru menginjakkan kakinya di Jembrana
tahun 1799 sampai beliau meninggal. Beliau sebagai seorang pemimpin
mempunyai kemampuan, bakat sehingga sangat dihormati oleh masyarakat.
D. PENUTUP
Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri (Syarif Tua) adalah salah seorang
tokoh yang berasal dari Pontianak. Beliau bersama anak buahnya berkelana
sampai di Loloan-Jembrana karena berbeda pandangan dengan Sultan
Pontianak Syarif Abdurrahman yang mau tunduk kepada pemerintah Belanda.
Kesepakatan untuk menandatangani kerjasama antara pemerintah Belanda
dengan Syarif Abdurrahman dilakukan pada tanggal 5 Juli 1779, sehingga
sejak itu Sultan Pontianak mengakui Kompeni sebagai tuannya. Pengakuan
Sultan Pontianak Syarif Abdurrahman terhadap pemerintah Belanda membuat
kecewa Syarif Abdullah bin Yahya Al Qodri (Syarif Tua), dan beliau
beserta anak buahnya memutuskan untuk membrontak kepada Belanda. Karena
terus dikejar-kejar Syarif Tua memutuskan untuk pindah ke daerah-daerah
yang belum dikuasai oleh pengaruh Belanda. Rombongan Syarif Tua
berlayar hingga sampai di Nusa Tenggara Barat dan terus ke barat sampai
di Air Kuning-Jembrana pada tahun 1799.
Beliau disambut dengan baik oleh penduduk yang sudah lama tinggal di
sana yang berasal dari suku Bugis bernama Haji Shihabuddin, serta
diantar menghadap kepada Raja Jembrana Anak Agung Putu Seloka. Setelah
menghadap raja, syarif Tua diijinkan menetap di Jembrana dan diberikan
tempat bermukim di kiri dan kanan Sungai Ijo Gading seluas 80 ha dengan
syarat Syarif Tua bersedia melakukan kerjasama dan membantu kerajaan
Jembrana dalam menghadapi musuh-musuhnya.
Setelah menetap di Loloan, Syarif Tua merubah perahu-perahu perangnya
menjadi perahu-perahu perniagaan dan beliau menjelajahi laut sampai ke
Singapura dan Tanah Melayu Malaisia. Lambat laun Bandar Pancoran menjadi
ramai berkat bantuan umat Muslim sehingga Jembrana menjadi salah satu
kerajaan yang sangat ramai karena perniagaannya. Untuk memperkuat
pertahanan Kerajaan Jembrana, Syarif Tua membangun sebuah benteng
pertahanan yang kuat dengan nama Benteng fathimah. Beliau beserta laskar
Muslimnya selalu ikut membantu di dalam peperangan-peperangan melawan
musuh-musuh Kerajaan Jembrana.
Kelurahan Loloan Jembrana adalah salah satu potret desa yang mampu
menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah-tengah penduduknya yang
majemuk baik Islam, Hindu, Protestan, Katolik dan Bhuda. Keberhasilan
kerukunan antar umat disini diwariskan secara turun-temurun sampai saat
ini terutama dalam kehidupan sehari-hari. Pembauran keragaman dalam
bingkai kesatuan wilayah inilah yang menjadi modal dalam pembangunan
Loloan dan Jembrana. Keterikatan historis merupakan perekat antar umat
beragama, dan hal ini perlu disadari dan dilestarikan untuk menjaga
kebersamaan dalam membangun Jembrana. Jangan sampai perbedaan menjadi
penghambat dalam segala hal khususnya dalam pembangunan di segala
bidang.
DAFTAR PUSTAKA
Agung, A.A. Gde Putra. 2001.“Teknik Penulisan Biografi”. Makalah
disampaikan Pada Forum Evaluasi dan Pembahasan Proposal Balai Kajian
Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar bekerjasama dengan Fakultas
Sastra Universitas Udayana dan UNHI di Denpasar, 20 Pebruari.
Agung, Anak Agung Ktut. 1991. Kupu-Kupu Kuning yang Terbang di Selat
Lombok: Lintasan Sejarah Kerajaan karangasem 1660 – 1950. Denpasar: PT.
Upada Sastra.
Buda, I Made. 1990. “Hubungan Antar Etnik di Jembrana 1856 – 1942”. Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar (Skripsi).
Damanhuri, A. 1993. “Sejarah Kelahiran Kota Negara”. Makalah Seminar yang disampaikan dalam seminar lahirnya Kota Negara.
Damanhuri, H. Achmad. 1993. “Sejarah Kelahiran Kabupaten Jembrana”.
Makalah diajukan untuk Bahan Seminar Sejarah Lahirnya Kabupaten Jembrana
dan Kota Negara.
Ginarsa, Ketut, Suparman Hs. 2002. “Umat Islam di Buleleng”. Dalam
Shaleh Saidi, Yahya Anshori (penynting). Sejarah Keberadaan Umat Islam
di Bali. Denpasar: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali.
Jayus, I Nyoman, I Ketut Suwentra. 1993. “Babad Tanah Jembrana”. Makalah
diajukan untuk Seminar Sejarah Lahirnya Kabupaten Jembrana dan Kota
Negara.
Kada, Thomas. 1982. Kepemimpinan Dalam Teori dan Praktek Serta Masalah-Masalahnya. Kupang: FKIP Undana.
Kantor Informasi Komunikasi dan Pelayanan Umum Kab. Jembrana. 2002.
Feature Mozaik Jembrana. Jembrana: Seksi Humas Kantor Inkom dan Yanum
Kab. Jembrana.
Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodelogi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kelurahan Loloan Timur. 2008. Laporan Bulanan Desa/Kelurahan. Negara.
Nyoka.1990. Sejarah Bali. Denpasar: Penerbit dan Toko Buku RIA.
Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Lapangan. 1996. “Laporan Kegiatan Kuliah
Kerja Lapangan (KKL) 1996 Jurusan Pendidikan Sejarah”. Jakarta: Fakultas
Pendidikan ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Jakarta.
Parisada Hindu Dharma. 1975. Pemargan Danghyang Nirartha di Bali (Dwi
Jendra Tatwa/Riwayat Danghyang Nirartha). Denpasar: Parisada Hindu
Dharma Kabupaten Badung.
Parwata, I Putu. 1994. “Sejarah Kota Negara 1958 – 1992”. Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar (Skripsi).
Puspawati, Ni Nyoman Suhendra. 1990. “Perkembangan Kesenian Jegog,
Kendang Mebarung, Bungbung Gebyog dan Atraksi Makepung di Kabupaten
Jembrana Tahun 1944 – 1979”. Fakultas Sastra Universitas Udayana
(Skripsi).
Putra, Ida Bagus Rai. 1991. Babad Dalem. Denpasar: PT. Upada Sastra.
Raka, I Gusti Gede. 1955. Monografi Pulau Bali. Djakarta: Bagian Publikasi Pusat DJawatan Pertanian Rakjat.
Reken, I Wayan. 2002. Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali. Denpasar: MUI Bali.
Sjafei, Suwadji. 1984. Pemikiran Biografi dan Kesejarahan, Suatu
Kumpulan Prasaran pada Berbagai Lokakarya Jilid III. Jakarta: Depdikbud
Ditjarahnitra, Proyek IDSN.
Soebantardjo, R. M.1983. Pemikiran Biografi dan Kesejarahan, Suatu
Kumpulan Prasaran pada Berbagai Lokakarya, Jilid I. Jakarta: Depdikbud
Proyek IDSN.
Sumarsono. 1993. Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan di Bali. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Sumerta, I Made, dkk. 2000. Tatakrama Suku Bangsa Loloan di Kabupaten
Jembrana Provinsi Bali. Denpasar: Depdiknas, Proyek P2NB Daerah Bali.
Suprayogo, Imam.1988.“Patron Klien Dalam Kepemimpinan”. Seluk Beluk Perubahan Sosial. Surabaya: Usaha nasional.
Suryawati, Cok Istri. 2003. “Biografi Tokoh Pejuang I Nyoman Mantik”.
Dalam Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional, Edisi Kesebelas
No. 11/III/2003. Denpasar: BKSNT Denpasar.
Suwita, I Putu Gede. 1997. “Loloan Bandar Laut, dan Hubungan Antara
Budaya”. Dalam Depdikbud RI. Kongres Nasional Sejarah 1996 Sub Tema
Dinamika Sosial Ekonomi III. Jakarta: Depdikbud RI.
Swarsi, S. dkk. 1998/1999. “Sejarah Kerajaan Tradisional Bali (Kerajaan
Karangasem)”. Denpasar: Depdikbud, Proyek Iventarisasi dan dokumentasi
Sejarah Nasional.
Tim Penulis. 1997. “Sejarah Jembrana dan Lahirnya Ibukota Negara”.
Jembrana: Bagian Pemerintahan Pemda Tinkkat II Kabupaten Jembrana.
Toetoer Lambangkawi (transkripsi). Koleksi Gedong Kirtya Singaraja, No. 1339/Va.
Wirawan, A.A.B., Dian Arriegalung. 2002. Umat Islam di Badung”. Dalam
Saleh Saidi, Yahya Anshori. Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali.
Denpasar: Majelis Umat Islam Bali.
Langganan:
Postingan (Atom)
-
AHMAD AL-HADI Pendiri NU Pertama di Bali Ahad, 01/04/2007 10:22 Lahir pada tahun 1899 dari ...
-
Dunia sebentar lagi akan berakhir. Manfaatkanlah akhir waktumu Untuk mencari bekal pada perjalanan berikutnya. JANGAN MENJADI OR...